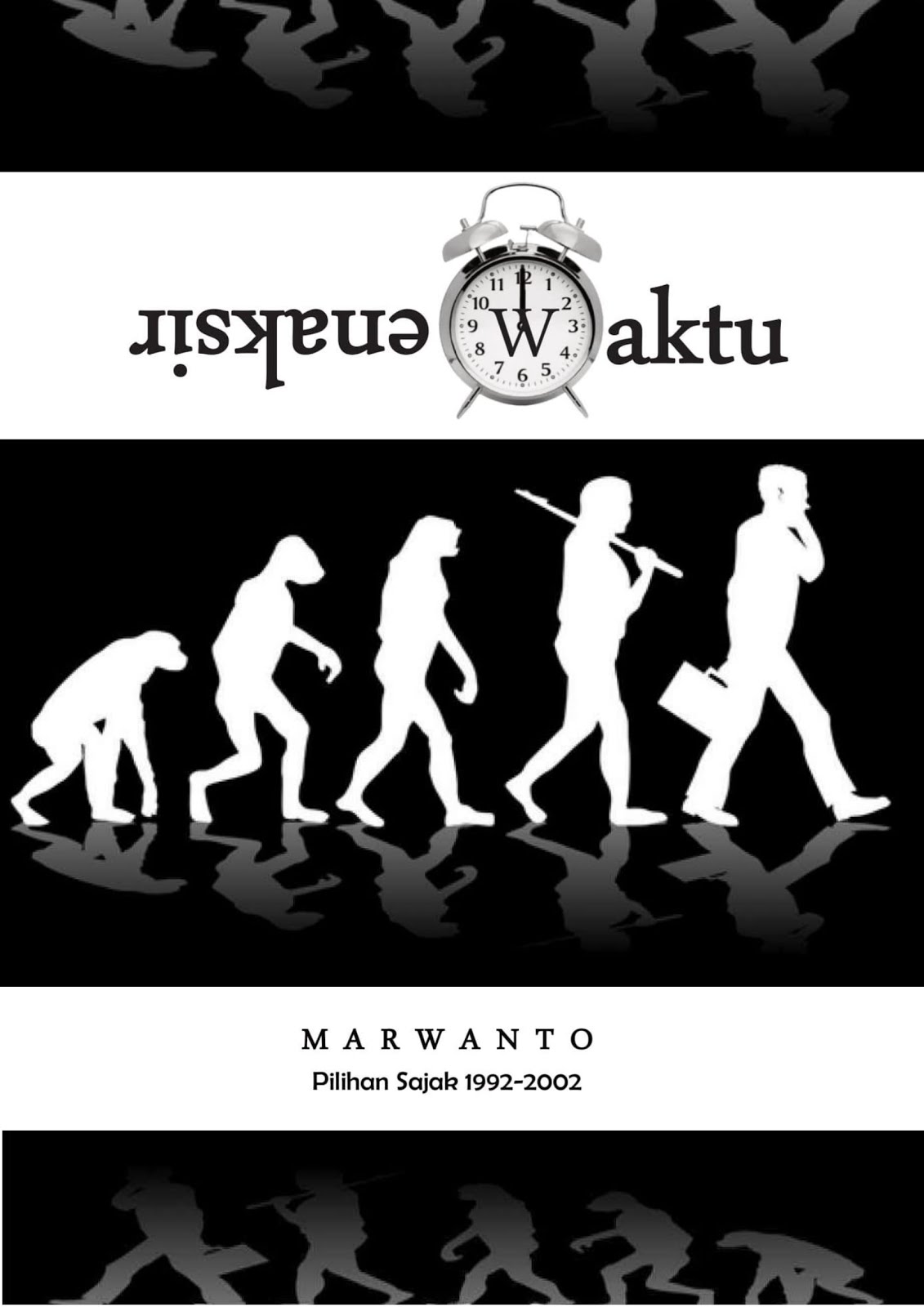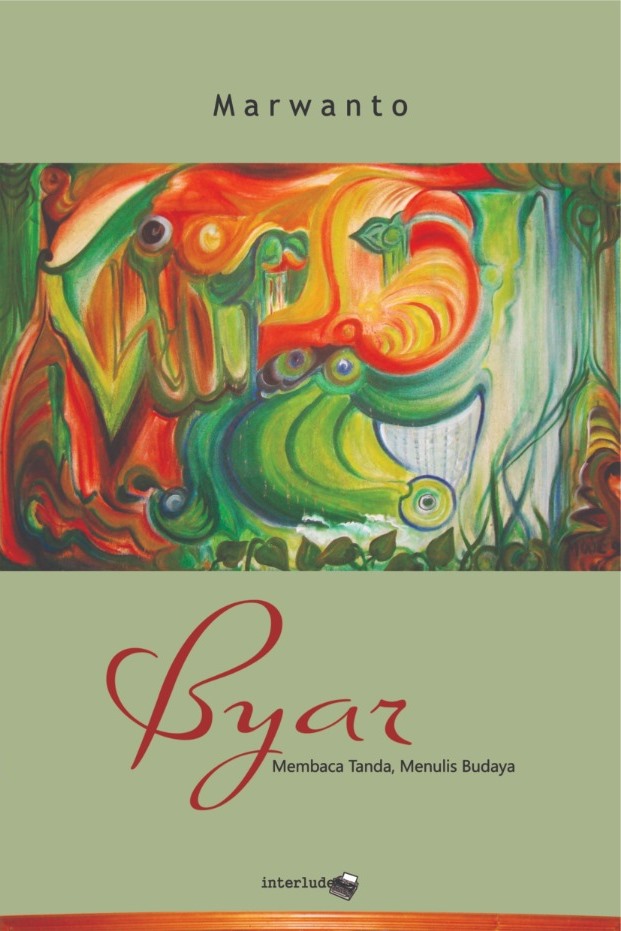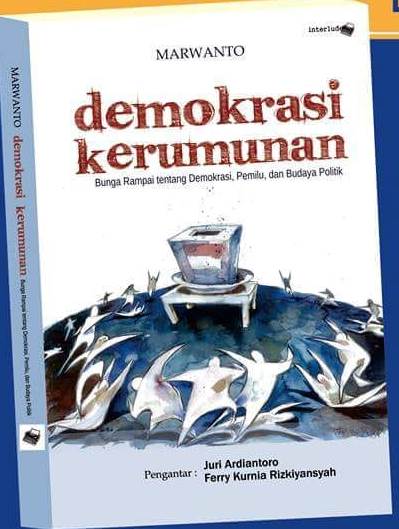Warna
Dulu saya sering berpikiran (mungkin ini sebentuk kecengengan) begini: dua warna yang sama ketika digabung menjadi satu tak kan menimbulkan warna lain. Misal: warna putih dibaurkan dengan putih, hasilnya tentu juga putih. Sementara dua warna yang berbeda, jika dicampur, akan menghasilkan warna yang sama sekali lain: warna biru dan kuning, kalau kita oplos maka hasilnya hijau. Menurut guru gambar saya, fenomena oplos warna ini tak hanya berlaku di dunia lukis, tapi juga pada kehidupan sehari-hari.
Awalnya, mungkin karena kecengengan pula, saya memercayai “hukum” ini. Namun kini, seiring bertubi-tubinya peristiwa yang datang menghunjam tak sesuai kaidah oplosan warna tersebut, saya berani berkata non-sens pada apa yang dikatakan guru gambar saya. “Ah teori”, kata sepenggal iklan yang dulu sempat kondang. Persoalannya tentu tak terletak pada “menerima” atau “menolak” hukum tersebut. Tapi, mengapa hal demikian bisa terjadi?
Konon, Romeo dan Juliet –juga kisah asmara lain yang menggetarkan-- berangkat dari rasa (warna) yang sama: cinta. Namun, alih-alih mereka bisa membangun mahligai, justru yang mereka temui adalah akhir yang tragis? Pada kehidupan kenegaraan: tak ada satu partai politik pun yang punya asas dan landasan perjuangan bersifat “nista”, namun mengapa pentas politik selalu tak jauh dari main kayu dan praktik dagang sapi? Dan contoh yang sulit kita tampik: sejumlah aliran keagamaan sama-sama ingin mempergelarkan tatanan kehidupan berdasar firman Tuhan, tapi mengapa yang terjadi adalah saling menghunus pedang?
Dalam koteks ini, saya tak hendak memberi argumentasi: bahwa gagalnya mereka membaurkan warna yang sama karena mereka baru berangkat pada tataran konsep (akan warna) yang sama, tapi miskin bahkan nol dalam praktik. Agaknya, radikalisme logika mesti kita arahkan pada: bahwa diantara mereka yang hendak “menyatu” membawa warna yang sama tadi terbentang jarak. Dan jarak adalah “warna” itu sendiri. Perjuangan menempuh jarak adalah pergulatan merangkai warna kehidupan. Semakin jauh dan intens seseorang menempuh, mengolah dan menggauli jarak (di sini jarak tidak mesti diukur dengan parameter fisik seperti kilometer dsb), kian berwarna pula kehidupannya. Dan ketika kehidupan seseorang makin berwarna, bukan tidak mungkin ia bisa mencapai pada kesimpulan: bahwa sejatinya warna-warni itu hanya pantulan dari Yang Maha Cahaya.
Daun itu sejatinya tak berwarna hijau, ia hanya memantulkan Cahaya Hijaunya Tuhan. Sementara Cahaya Kuning Tuhan, dipantulkanlah oleh kenanga. Dan seterusnya. Demikian pesan orang bijak. Pertanyaannya: warna buram kehidupan ini pantulan dari mana? Ya, bagi insan yang taat, ia tak berjarak dengan Tuhan. Tapi bagi yang ingkar, jarak-jarak yang mereka ciptakan membuat warna kehidupan terasa berat untuk dibelai dengan kasih sayang.***
SUMBER: Buletin Sastra Lontar Edisi 14/Tahun II/2008
Minggu, 03 Februari 2008
Langganan:
Postingan (Atom)