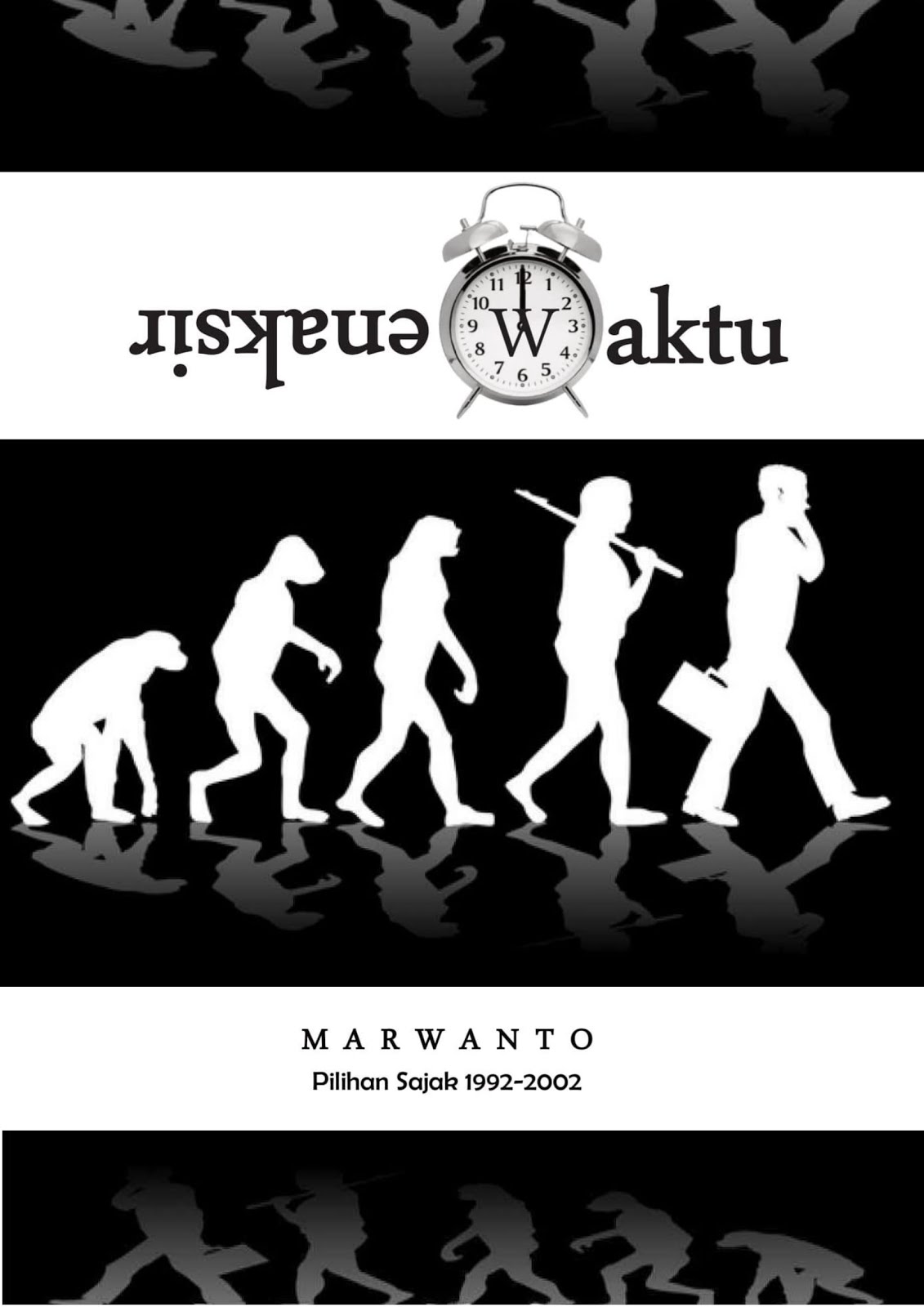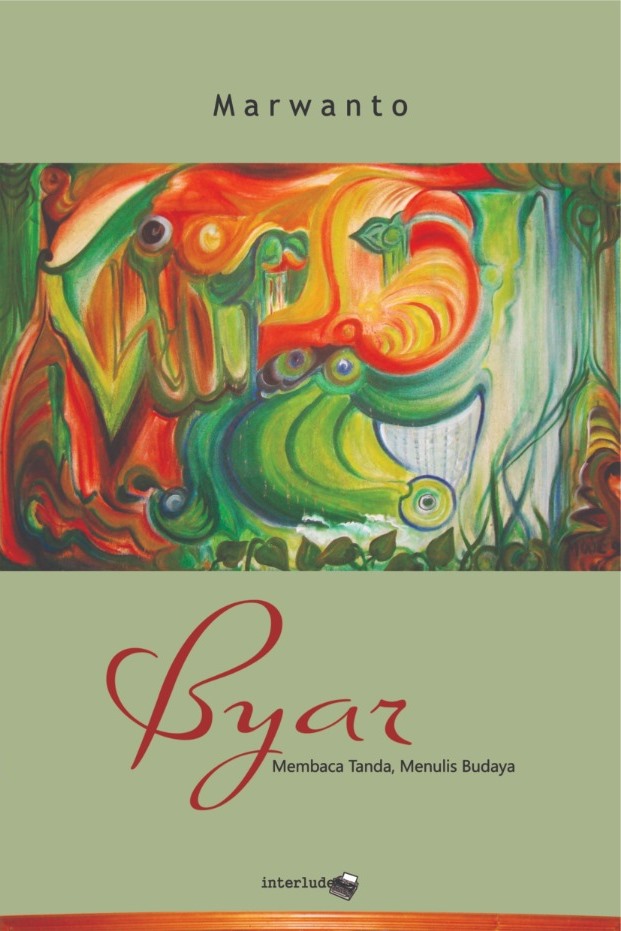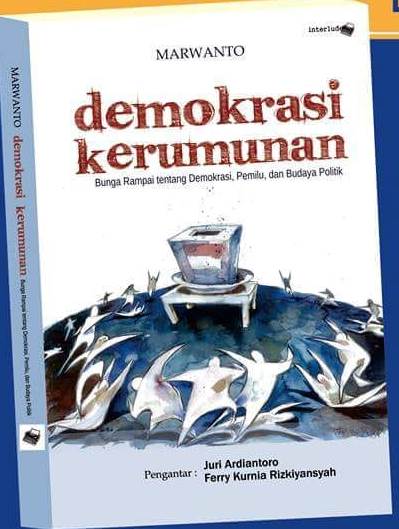Rindu Rumput Halaman
(KOMPAS (Halaman YOGYA), 23 /06/2008)
Beberapa waktu lalu saya dan sejumlah penulis dari Kulonprogo berkunjung ke rumah (baca: kamar kos) penyair Iman Budhi Santosa di Dipokusuman. Ada dua hal yang menjadi ciri menonjol kos-kosan Mas Iman: pohon sawo yang cukup besar menjulang tinggi dan halamannya yang luas. Ya, halaman berupa tanah yang kalau hujan datang pasti becek tak terelakkan.
“Saya sengaja memilih halaman yang tidak ber-konblok”,
“Lho, bukannya halaman yang ada kon-bloknya akan terlihat rapi dan bersih?”
“Iya, memang. Tapi, masa’ rumput saja dilarang tumbuh….” demikian Mas Iman berdalih pada kami.
Rumput. Jenis tumbuhan ini memang masih bisa tumbuh di halaman rumah-rumah perkotaan, meski halaman tersebut berkon-blok. Sebab, rumput akan dengan jeli tumbuh diantara himpitan kon-blok atau dimana saja area yang memungkinkan ia tumbuh. Tapi, saya kira tidak demikian maksud pernyataan Mas Iman. Apa yang dikatakan Mas Iman seakan sedang “mengoreksi” pemahaman kita akan kecintaan terhadap tanaman.
Ya, sejak booming tanaman (hias) beberapa waktu lalu, hampir tiap orang beramai-ramai “mencitai tanaman”. Rumah-rumah disulap dan dipenuhi aneka tanaman hias. Lalu ada imej: bahwa rumah beserta penghuninya sedang ramah lingkungan dengan banyaknya aneka tanaman (hias) dijejer di halaman sampai ruang tamu. Tapi, benarkah mereka benar-benar mencintai tanaman? Bukankah dengan “melarang” rumput tumbuh di halaman dengan memasang kon-blok, kita sejatinya mengekang tanaman?
Mencintai memang tidak gampang. Begitu juga mencintai tanaman dan lingkungan. Salah-salah, yang kita lakukan adalah menegakkan ego: mereka (tanaman) kita perlakukan sebagai objek penderita demi kesenangan dan hobi kita semata. Di sisi lain, hak tumbuh mereka secara wajar terus kita kebiri bahkan kita sumbat dan kekang.
Bagi orang yang menyuntukkan diri di dunia kreatif, seperti mas Iman, perilaku mencintai seperti itu jelas sangat bertentangan. Dunia kreatif sangat membenci kekangan. Di sini, Mas Iman adalah antitesa terhadap sikap mencitai tanaman (lingkungan) yang menjadikan tanaman sekedar objek penderita. Barangkali seperti tata kelola kota yang “mengharuskan” segala yang hidup tunduk pada logika dan konsep-konsep perkembangan kota modern.
Benarkah orang semacam Mas Iman adalah antitesa terhadap logika kehidupan kota? Mas Iman hanya salah satu amsal. Saya yakin masih ada orang lain seperti Mas Iman. Mereka ini akan terus memilih tinggal pada pekarangan yang di situ ada rumputnya. Dengan tinggal di tanah yang berumput, Mas Iman bisa terus selalu berkarya (menulis) sambil memandang pohon sawo atau rumput belukar di depan kamar kos-nya. Mungkin sambil menahan “letih” merasakan laju perkembangan kota dengan mengutip sebaris sajak Federico Garcia Lorca: Verde que te quiero verde…: Hijau, kumau engkau hijau://Bintang agung beku dingin//Tiba dengan bayang ikan//Yang merintis fajar.
Minggu, 27 Juli 2008
Kolom BYAR
Kethoprak
( Utik TW )
Ajakan nonton kethoprak. Itulah SMS terakhir yang kuterima darimu. Sebelum kau berpulang –pada sebuah pagi yang tak lagi dingin. Matahari, di pagi itu, telah senyum begitu lebar. Ah, bahkan tertawa. Ya, seperti tawamu yang amat lepas: ketika kita sedang tadarus puisi, menyiapkanTBM atau menggarap laporan PMK yang tak kunjung rampung. Dan di jalan Deandeles itu agaknya kau juga tertawa –meski dalam dekapan malaikat--, tawa yang terakhir.
Dan bukankah kethoprak (setidaknya dalam perspektif modern) mengajak kita tertawa? Mungkin memang bukan yang utama. Tapi, dalam konotasi tertentu, tawa dalam istilah kethoprak tidak bisa sekedar disebut bumbu. Simak misalnya dalam ungkapan: “Wah, malah kethoprak-an” atau “Jangan sok kethoprak-an, ah”. Ungkapan tersebut sering diartikan: jangan membuat lelucon. Akhirnya, pada tafsir kontemporer, acapkali seni kethoprak direduksi sekedar (pentas) lelucon.
Padahal, pada awal kemunculannya, kethoprak bukanlah berisi cerita yang cuma mengajak kita tertawa. Konon, sejarah kethoiprak yang bergulir tahun 1887 dengan jenis kethoprak lesung, dimulai dengan mengusung tema-tema “serius”: babad, legenda, dan adaptasi karya pujangga ternama semacam Pangeran Hamlet karya Shakespeare. Tapi, dalam perkembangnnya kethoprak diidentikan pentas yang mengusung lelucon. Muncullah kethoprak plesetan dan kethoprak humor.
Hal ini agaknya karena kehidupan yang kian pragmatis dan gersang. Dalam pragmatisme hidup, mengusung keseriusan ibarat berteriak ditengah gemuruh gelombang. Dan di dunia yang telah gersang, sesuatu yang serius acapkali membuat kram otak. Sebaliknya, lelucion/humor menjadi segelas es pelepas dahaga. Lalu dengan ditunjang perkembangan audio visual, pentas kethoprak meraih booming. Tapi, kejemuan memang gejala alamiah. Publik pun bosan. Masyarakat muak. Kethoprak tak lagi lucu. Sebab kehidupan nyata itu sendiri yang kemudian menjelma lelucon. Dan, dalam konteks ini, Utik tak salah: menyikapi dunia yang letih dengan tawa yang lepas.
Ah, Utik. Mungkin teman-teman lebih mengenangmu sebagai aktivis yang tak jenak diam (mobilitas telah identik dengan dirimu) atau kedua tahi lalat di pipimu. Namun ijinkan aku selalu terkenang dengan tawamu. Seperti di sore itu, memang ada isak dan air mata mengiringi jenazahmu –tapi selanjutnya yang terngiang adalah tawamu. Tawamu yang khas. Mengingatkanku pada pepatah Yahudi: saat manusia berpikir, Tuhan tertawa.***
Sumber: Buletin Sastra LONTAR Edisi 19/Th.II/2008
( Utik TW )
Ajakan nonton kethoprak. Itulah SMS terakhir yang kuterima darimu. Sebelum kau berpulang –pada sebuah pagi yang tak lagi dingin. Matahari, di pagi itu, telah senyum begitu lebar. Ah, bahkan tertawa. Ya, seperti tawamu yang amat lepas: ketika kita sedang tadarus puisi, menyiapkanTBM atau menggarap laporan PMK yang tak kunjung rampung. Dan di jalan Deandeles itu agaknya kau juga tertawa –meski dalam dekapan malaikat--, tawa yang terakhir.
Dan bukankah kethoprak (setidaknya dalam perspektif modern) mengajak kita tertawa? Mungkin memang bukan yang utama. Tapi, dalam konotasi tertentu, tawa dalam istilah kethoprak tidak bisa sekedar disebut bumbu. Simak misalnya dalam ungkapan: “Wah, malah kethoprak-an” atau “Jangan sok kethoprak-an, ah”. Ungkapan tersebut sering diartikan: jangan membuat lelucon. Akhirnya, pada tafsir kontemporer, acapkali seni kethoprak direduksi sekedar (pentas) lelucon.
Padahal, pada awal kemunculannya, kethoprak bukanlah berisi cerita yang cuma mengajak kita tertawa. Konon, sejarah kethoiprak yang bergulir tahun 1887 dengan jenis kethoprak lesung, dimulai dengan mengusung tema-tema “serius”: babad, legenda, dan adaptasi karya pujangga ternama semacam Pangeran Hamlet karya Shakespeare. Tapi, dalam perkembangnnya kethoprak diidentikan pentas yang mengusung lelucon. Muncullah kethoprak plesetan dan kethoprak humor.
Hal ini agaknya karena kehidupan yang kian pragmatis dan gersang. Dalam pragmatisme hidup, mengusung keseriusan ibarat berteriak ditengah gemuruh gelombang. Dan di dunia yang telah gersang, sesuatu yang serius acapkali membuat kram otak. Sebaliknya, lelucion/humor menjadi segelas es pelepas dahaga. Lalu dengan ditunjang perkembangan audio visual, pentas kethoprak meraih booming. Tapi, kejemuan memang gejala alamiah. Publik pun bosan. Masyarakat muak. Kethoprak tak lagi lucu. Sebab kehidupan nyata itu sendiri yang kemudian menjelma lelucon. Dan, dalam konteks ini, Utik tak salah: menyikapi dunia yang letih dengan tawa yang lepas.
Ah, Utik. Mungkin teman-teman lebih mengenangmu sebagai aktivis yang tak jenak diam (mobilitas telah identik dengan dirimu) atau kedua tahi lalat di pipimu. Namun ijinkan aku selalu terkenang dengan tawamu. Seperti di sore itu, memang ada isak dan air mata mengiringi jenazahmu –tapi selanjutnya yang terngiang adalah tawamu. Tawamu yang khas. Mengingatkanku pada pepatah Yahudi: saat manusia berpikir, Tuhan tertawa.***
Sumber: Buletin Sastra LONTAR Edisi 19/Th.II/2008
Langganan:
Postingan (Atom)