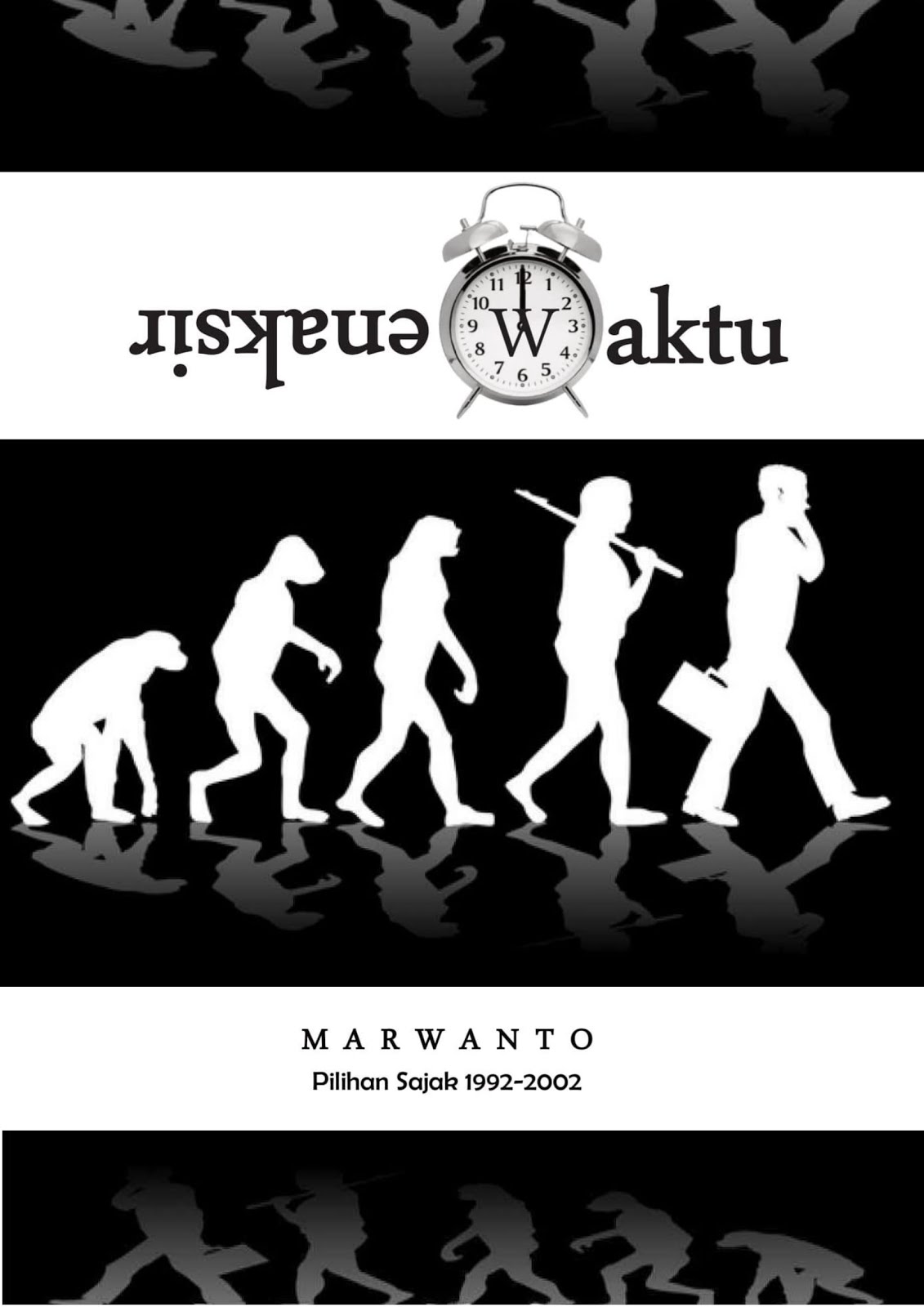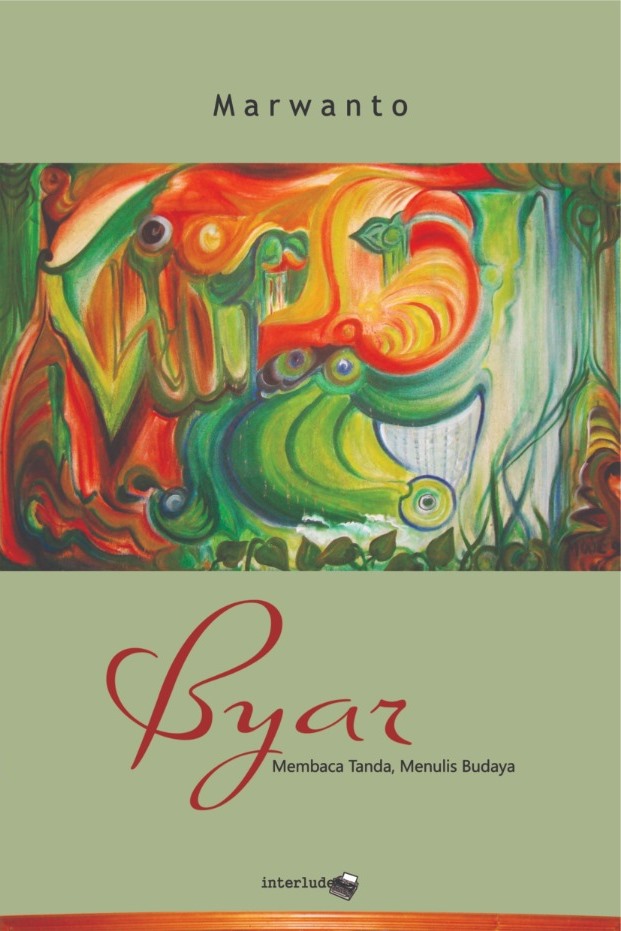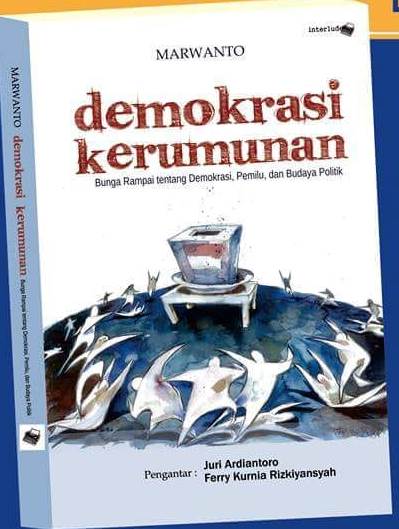Kota dan Dusta
oleh Marwanto
(Kompas (halaman Yogyakarta), 26/11/2008)
Kota adalah lanskap dimana setiap anasir di dalamnya selalu bergerak, dinamis, dan penuh mobilitas. Orang-orang yang berjalan kaki selalu terlihat lebih cepat dari yang kita temui di jalan-jalan pedesaan. Kalaupun ada pejalan kaki yang terlihat lamban di jalan-jalan kota, mereka pasti seorang pengemis atau pemulung yang menjadi korban ritme hidup perkotaan. Atau dua sejoli yang kasmaran dan sedang melupakan hiruk-pikuk keramaian sekitar.
Namun kota juga bisa hadir (dan kita pandang) sebagai bentangan ribuan etalase Yang membuat kita diam, tertegun, dan bengong. Kota mendorong kita untuk berkhayal. Kota adalah gudang ilusi, seperti setting sebagian besar sinetron televisi kita. Meskipun kota sebagai sesuatu yang dicitakan, ia masih membuat kita --masyarakat kebanyakan-- tertegun dan bengong.
Sehingga tak berlebihan jika para pemikir melihat kota adalah konsekuensi fisik dan sosial sekaligus dari kapitalisme. Kapitalisme, dengan industrialisasi sebagai “mesinnya”, secara psikologis memang menghadirkan khayal. Tidak saja gedung-gedung pencakar langit, tower yang menjulang, serta jalan tol mulus, tapi juga papan reklame dan ribuan etalase yang mendorong manusia menciptakan khayal. Lalu, reaksi yang bagaimana yang jamak ditempuh manusia dalam kondisi demikian ?
Ketika orang kampung dari pedalaman Gunung Kidul atau Kulon Progo jalan-jalan di Malioboro dan memandang gemerlap reklame (Dian Sastro yang mengiklankan sabun misalnya), ia sejatinya tak hanya berhenti menatap seorang Dian Sastro. Di dalam file-file otaknya lambat laun terbentuk citra tentang ide kecantikan yang sempurna, yang diidamkan. Kebetulan yang hadir saat itu adalah Dian Sastro.
Maka saat ia pulang kampung, lahirlah trend meniru apa yang dipakai dan dilakukan artis tadi. Kalaupun ia tak secantik Dian Sastro, ia cukup bangga saat menggosokkan sabun yang dipakai Dian Sastro. Itulah reaksi kebanyakan orang dalam menghadapi konsekuensi kapitalisme. Dalam ketakmampuan, orang masih bisa menghibur diri: dengan ilusinya mencipta imej atau citra dalam kesemuan (pseudo). Ironisnya, kesemuan itu acapkali dipandang sebagai realitas dan dijadikan dasar tindakan.
Meski menimbulkan ironisme, tapi kapitalisme memang tak seharusnya dilawan secara membabi-buta: dengan perusakan dan pengeboman tempat hiburan misalnya. Kapitalisme justru bisa menjadi salah satu sparing patner manusia untuk menegakkan eksistensinya. Dalam konteks ini, maka cukup masuk akal jika ada usulan bahwa untuk menunjukkan keistimewaan Yogyakarta perlu mentransfer semangat kepeloporan keraton dan keberanian rakyat Yogya dalam menentang kolonialisme masa lalu untuk menghadapi neo-kolonialisme baru: globalisasi dan ekspansi pasar atau liberalisasi, wajah lain kapitalisme.
Manakala kita gagal menjadikan kapitalisme sebagai sparing patner, kita hanya akan menjadi bagian dari ekornya. Padahal kapitalisme, dengan “kultur kota” sebagai salah satu penampakannya (menurut Nikolai Gogol dalam salah satu cerita pendeknya) adalah bohong selamanya. Sebuah “kota” adalah seribu ilusi, sekaligus dusta yang memikat.***
Rabu, 26 November 2008
Jumat, 21 November 2008
OPINI
Obsesi Menjadi PNS
Oleh Marwanto
(Radar Jogja, 21/11/2009)
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali dibuka. Kabar ini segera disambut antusias oleh banyak pihak di negeri ini –suatu fenomena yang menunjukkan bahwa status sebagai PNS masih menjadi obsesi sebagian besar masyarakat kita. Pertanyaannya, mengapa di era sekarang status PNS masih diminati sebagian besar masyarakat?
Pertanyaan tersebut akan menghantarkan kita pada telaah mengenai sejarah panjang birokrasi di negara ini. Prof. Kuntowijoyo dalam bukunya Demokrasi dan Budaya Birokrasi, menjelaskan untuk memahami birokrasi di negara kita perlu disimak tiga fase perkembangannya. Tiga fase tersebut meliputi: masa kerajaan, masa kolonial dan masa negara nasional. Dari sini diketahui bahwa corak (kultur) birokrasi kita saat ini merupakan warisan birokrasi model kerajaan –terutama kerajaan agraris.
Pada zaman kerajaan, kedudukan birokrasi disebut dengan nama abdi dalem, sebuah istilah yang lebih berorientasi melayani raja daripada rakyat. Dalam perjalanan waktu, para abdi dalem ini menjadi kelas sosial tersendiri yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Apalagi, kedudukannya kemudian diperkuat dengan berbagai atribut yang diperoleh dari kerajaan, misalnya dengan diberi pangkat atau gelar..
Fase kedua, ketika penjajah datang (masa kolonial), birokrasi dikenal dengan sebutan priyayi atau ambtenaar. Sama halnya dengan abdi dalem, priyayi juga mempunyai kedudukan/satuts yang istimewa dalam masyarakat. Selain itu, para priyayi juga sering menempatkan dirinya sebagai bagian dari kekuasaan kolonial, sebagaimana para abdi dalem menganggap dirinya bagian dari kekuasaan kerajaan.
Terakhir, ketika negara nasional terbentuk, birokrasi kita dikenal dengan nama pegawai negeri. Sama seperti dua masa sebelumnya, pegawai negeri juga memiliki strata sosial yang khusus dibanding masyarakat kebanyakan. Kalau kita simak berbagai kegiatan (hajatan) yang ada di masyarakat sekitar, maka akan selalu melibatkan orang yang dianggap terpandang. Dan salah satu segmen dari orang terpandang tersebut adalah mereka yang berstatus sebagai PNS ! Jadi, meski telah ada berbagai perubahan (reformasi) di negeri ini, sama seperti abdi dalem maupun priyayi, pegawai negeri juga acapkali mengidentikan dirinya bagian dari kekuasaan (status-quo).
Menyimak sejarah birokrasi kita yang amat panjang tersebut, ada satu benang merah yang dapat ditarik: bahwa kedudukan atau status sebagai birokrat sering diidentikan dengan menjadi bagian dari sebuah kekuasaan. Dan menjadi bagian dari kekuasaan, di manapun dan kapapun (terutama pada masa sulit atau tak menentu seperti saat ini) akan membuat seseorang merasa aman atau terjamin hidupnya.
Keyakinan seperti ini terutama akan diterima dengan sangat baik (taken for granted) oleh mereka yang memiliki mentalitas agraris. Sesuatu yang nyata-nyata bertolak belakang dari mentalitas (jiwa) wiraswasta –yang meski bisa membuat orang bebas (mandiri) berusaha, tapi penuh spekulasi dan kondisi yang tak pasti. Sementara seperti kita ketahui, saat ini mayoritas masyarakat kita masih bermental agraris. Itulah mengapa setiap ada lowongan CPNS selalu disambut antusias oleh masyarakat.
Kondisi ini sebenarnya bisa kontra-produktif bagi perjalanan bangsa ke depan. Sebagaimana kita tahu, waktu-waktu mendatang bersamaan dengan diberlakukannya pasar bebas yang berdampak makin ketatnya persaingan hidup (berusaha), tentu akan menuntut hadirnya orang-orang yang berjiwa atau punya mentalitas berwiraswasta. Orang-orang yang mandiri, kreatif, tangguh, dan tahan banting. Pendek kata, generasi yang tak hanya bersandar atau menggantungkan hidupnya pada pemerintah (negara).
Tentu obsesi dan pilihan hidup menjadi seorang pegawai negeri adalah sah-sah saja. Namun satu hal yang harus dicatat: ketika obsesi menjadi pegawai negeri hanya karena dilandasi ingin hidupnya aman, tak kena PHK, meski malas kerja tetap dapat gaji, dan dekat dengan kekuasaan, maka disitulah telah tertanam benih bagi timbulnya patologi (penyakit) birokrasi. Mengapa? Sebab kinerja birokrasi akan lebih berorientasi ke atas (kekuasaan) daripada ke bawah (melayani rakyat).
Dari penelitian (untuk keperluan skripsi) yang pernah saya lakukan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya patologi birokrasi, sebagian besar karena orientasi aparatur negara lebih kepada melayani atau membuat senang kekuasaan daripada memberi layanan yang memuaskan pada publik. Dengan kata lain, semboyan abdi negara lebih ditonjolkan dibanding abdi masyarakat
Semoga seleksi penerimaan CPNS kali ini mampu menghasilkan para aparatur negara yang benar-benar beriktikad memberi layanan pada publik daripada sekedar membuat senang kekuasaan. Untuk mencapai tujuan ini, maka harus dimulai dengan transparansi rekruitmen PNS !***
Oleh Marwanto
(Radar Jogja, 21/11/2009)
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali dibuka. Kabar ini segera disambut antusias oleh banyak pihak di negeri ini –suatu fenomena yang menunjukkan bahwa status sebagai PNS masih menjadi obsesi sebagian besar masyarakat kita. Pertanyaannya, mengapa di era sekarang status PNS masih diminati sebagian besar masyarakat?
Pertanyaan tersebut akan menghantarkan kita pada telaah mengenai sejarah panjang birokrasi di negara ini. Prof. Kuntowijoyo dalam bukunya Demokrasi dan Budaya Birokrasi, menjelaskan untuk memahami birokrasi di negara kita perlu disimak tiga fase perkembangannya. Tiga fase tersebut meliputi: masa kerajaan, masa kolonial dan masa negara nasional. Dari sini diketahui bahwa corak (kultur) birokrasi kita saat ini merupakan warisan birokrasi model kerajaan –terutama kerajaan agraris.
Pada zaman kerajaan, kedudukan birokrasi disebut dengan nama abdi dalem, sebuah istilah yang lebih berorientasi melayani raja daripada rakyat. Dalam perjalanan waktu, para abdi dalem ini menjadi kelas sosial tersendiri yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Apalagi, kedudukannya kemudian diperkuat dengan berbagai atribut yang diperoleh dari kerajaan, misalnya dengan diberi pangkat atau gelar..
Fase kedua, ketika penjajah datang (masa kolonial), birokrasi dikenal dengan sebutan priyayi atau ambtenaar. Sama halnya dengan abdi dalem, priyayi juga mempunyai kedudukan/satuts yang istimewa dalam masyarakat. Selain itu, para priyayi juga sering menempatkan dirinya sebagai bagian dari kekuasaan kolonial, sebagaimana para abdi dalem menganggap dirinya bagian dari kekuasaan kerajaan.
Terakhir, ketika negara nasional terbentuk, birokrasi kita dikenal dengan nama pegawai negeri. Sama seperti dua masa sebelumnya, pegawai negeri juga memiliki strata sosial yang khusus dibanding masyarakat kebanyakan. Kalau kita simak berbagai kegiatan (hajatan) yang ada di masyarakat sekitar, maka akan selalu melibatkan orang yang dianggap terpandang. Dan salah satu segmen dari orang terpandang tersebut adalah mereka yang berstatus sebagai PNS ! Jadi, meski telah ada berbagai perubahan (reformasi) di negeri ini, sama seperti abdi dalem maupun priyayi, pegawai negeri juga acapkali mengidentikan dirinya bagian dari kekuasaan (status-quo).
Menyimak sejarah birokrasi kita yang amat panjang tersebut, ada satu benang merah yang dapat ditarik: bahwa kedudukan atau status sebagai birokrat sering diidentikan dengan menjadi bagian dari sebuah kekuasaan. Dan menjadi bagian dari kekuasaan, di manapun dan kapapun (terutama pada masa sulit atau tak menentu seperti saat ini) akan membuat seseorang merasa aman atau terjamin hidupnya.
Keyakinan seperti ini terutama akan diterima dengan sangat baik (taken for granted) oleh mereka yang memiliki mentalitas agraris. Sesuatu yang nyata-nyata bertolak belakang dari mentalitas (jiwa) wiraswasta –yang meski bisa membuat orang bebas (mandiri) berusaha, tapi penuh spekulasi dan kondisi yang tak pasti. Sementara seperti kita ketahui, saat ini mayoritas masyarakat kita masih bermental agraris. Itulah mengapa setiap ada lowongan CPNS selalu disambut antusias oleh masyarakat.
Kondisi ini sebenarnya bisa kontra-produktif bagi perjalanan bangsa ke depan. Sebagaimana kita tahu, waktu-waktu mendatang bersamaan dengan diberlakukannya pasar bebas yang berdampak makin ketatnya persaingan hidup (berusaha), tentu akan menuntut hadirnya orang-orang yang berjiwa atau punya mentalitas berwiraswasta. Orang-orang yang mandiri, kreatif, tangguh, dan tahan banting. Pendek kata, generasi yang tak hanya bersandar atau menggantungkan hidupnya pada pemerintah (negara).
Tentu obsesi dan pilihan hidup menjadi seorang pegawai negeri adalah sah-sah saja. Namun satu hal yang harus dicatat: ketika obsesi menjadi pegawai negeri hanya karena dilandasi ingin hidupnya aman, tak kena PHK, meski malas kerja tetap dapat gaji, dan dekat dengan kekuasaan, maka disitulah telah tertanam benih bagi timbulnya patologi (penyakit) birokrasi. Mengapa? Sebab kinerja birokrasi akan lebih berorientasi ke atas (kekuasaan) daripada ke bawah (melayani rakyat).
Dari penelitian (untuk keperluan skripsi) yang pernah saya lakukan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya patologi birokrasi, sebagian besar karena orientasi aparatur negara lebih kepada melayani atau membuat senang kekuasaan daripada memberi layanan yang memuaskan pada publik. Dengan kata lain, semboyan abdi negara lebih ditonjolkan dibanding abdi masyarakat
Semoga seleksi penerimaan CPNS kali ini mampu menghasilkan para aparatur negara yang benar-benar beriktikad memberi layanan pada publik daripada sekedar membuat senang kekuasaan. Untuk mencapai tujuan ini, maka harus dimulai dengan transparansi rekruitmen PNS !***
Selasa, 11 November 2008
OPINI
Masih Adakah Sosok “Pahlawan”?
Oleh Marwanto
(Kedaulatan Rakyat, 11 /11/2008)
Tak ada lencana yang lebih menawan dalam kebudayaan nasional modern daripada monumen-monumen dan makam-makan para tentara yang tak dikenal. Sekalipun makam tersebut menyimpan peninggalan mati yang tak dikenal atau jiwa-jiwa kosong, bagaimanapun makam-makan tersebut telah dipenuhi dengan khayalan nasional yang menghantui.
Paragraf di atas merupakan pendapat Benedict Anderson yang saya kutip dari buku karya Ross Poole, Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme (1993: 119). Lewat pendapat tersebut, tentu Ben Anderson tak sedang memuja seonggok benda mati bernama monumen. Tidak pula memuja kegagahan seorang tentara. Namun satu hal pasti: bagaimanapun epos kepahlawanan telah menjadi salah satu “ruh” dalam episode sejarah sebuah bangsa. Pembicaraan sejarah suatu bangsa tak akan lengkap tanpa membicarakan para pahlawan. Pada akhirnya, sosok pahlawan telah dan selalu menghantui perjalanan sebuah bangsa.
Maka, tak mengherankan jika dalam tiap periode sejarah dari sebuah negara-bangsa, banyak orang ingin tampil sebagai pahlawan. Tentu, seiring dengan perubahan jaman, maka makna dan sosok pahlawan akan selalu mengalami perubahan. Dulu, orang yang disebut pahlawan adalah mereka yang berjasa dalam pertempuran mengusir penjajah atau menghantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan. Lalu, di jaman sekarang ini, siapakah yang pantas disebut pahlawan ?
Tak mudah menjawabnya. Tapi yang pasti, dari dulu hingga sekarang, seorang pahlawan itu berangkat dari nilai. Pahlawan berjuang dan berkorban untuk menegakkan nilai. Nilai apakah yang ingin ditegakkan oleh seorang pahlawan ? Dari orang-orang bijak kita tahu jawabnya adalah nilai keadilan. Perjuangan dan pengorbaan pahlawan berujung pada terciptanya keadilan bagi umat manusia di muka bumi. Atas dasar titik pijak inilah, maka para pahlawan kita di jaman revolusi memperjuangkan kemerdekaan karena --seperti disebutkan dalam preambule konstitusi kita-- penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Jika kita selidiki lebih jauh, sejatinya keadilan sebagai sebuah nilai merupakan muara dari tiga nilai yang dalam kajian moralitas sering disebut sebagai “ide agung”. Prof Mortimer Jerome Adler dalam karyanya yang telah menjadi klasik The Great Ideas: A Syntopicon of Great Book of The Western World, 1952) menguraikan penyelidikannya tentang “ide agung” tersebut. Menurutnya, setidaknya ada tiga ide agung yang menyangga perdaban manusia, yakni: kebenaran, kebaikan dan keindahan. Nah, dengan tergelarnya tiga ide agung tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari maka dapat dipastikan keadilan juga telah maujud dalam kehidupan.
Dari kajian pustaka di atas, maka jika seseorang telah berjuang untuk menegak-kan kebenaran, kabaikan, dan keindahan demi terwujudnya keadilan di muka bumi maka ia sudah bisa disebut sebagai sosok pahlawan. Namun dalam aplikasinya ternyata amat sulit untuk melihat atau menemukan sosok penegak keadilan. Hal ini karena dalam menegakkan keadilan selalu disertai sebuah pertanyaan: keadilan untuk siapa ? Terlebih ketika rasa kebangsaan kita mulai pudar, maka perjuangan untuk menegakkan nilai menjadi amat partikular sifatnya. Dengan kata lain, menegakkan nilai untuk kepentingan bersama sebagai bangsa menjadi sesuatu yang amat mahal dan jarang (untuk tidak menyebut mustahil) untuk diperjuangkan.
Sebagai contoh kecil, seorang yang ingin memberantas kasus korupsi, tapi kebetulan pelakunya itu ada hubungan (entah kerabat atau kolega) dengan yang hendak memberantas maka tentu akan berpikir dua kali. Alih-alih menegakkan keadilan dengan memberantas korupsi, yang terjadi malah berusaha dengan segala cara (baik secara legal maupun kekuatan politik) untuk menghalang-halngi tindak pidana korupsi tersebut.
Alhasil, yang kemudian terjadi adalah munculnya pahlawan-pahlawan bagi suatu kelompok. Padahal, selain berangkat untuk menegakkan nilai, konsep kepahlawanan juga berangkat dari rasa senasib-sepenanggungan. Perjuangan dan pengorbanan tanpa dilandasi rasa senasib-sepenanggungan hanya akan melahirkan heroisme semu. Heroisme semu inilah yang kini sedang melanda kehidupan di tanah air.
Apalagi ketika salah satu buah dari reformasi politik di negeri kita meng-amanatkan jabatan publik dipilih secara langsung oleh rakyat, maka upaya untuk tampil dengan haroisme semu kian menjadi-jadi. Dalam konteks ini, heroisme cuma disepadankan dengan satu kata: popularitas ! Lihatlah, dari pemilihan presiden sampai kepala desa, maka faktor pertama-tama untuk mendulang suara adalah popularitas. Tentu tidak ada salahnya dengan faktor popularitas, namun yang amat disayangkan adalah popularitas itu acapkali sekedar citra (atau ‘tebar pesona”) yang dibuat lewat media massa dan kurang berhubungan dengan kualitas, terlebih kinerja dari seseorang.
Dari realita itulah maka kini sosok pahlawan telah mengalami pendangkalan makna. Sudah pasti pendangkalan makna kepahlawanan ini menerbitkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah sulitnya bangsa ini melakukan perubahan. Ya, karena masing-masing orang hanya mau jadi pahlawan buat kelompoknya atau memikirkan hal-hal yang membuat dirinya supaya tetap populer meski kinerjanya payah.
Di jaman yang serba sulit dimana kohesi sosial kita sebagai bangsa belum sepenuhnya pulih, memang sulit memunculkan sosok pahlawan “sejati”. Pahlawan yang berjuang dan berkorban untuk menegakkan nilai dengan dilandasi rasa senasib-sepenanggungan dan buat kepentingan bersama. Tapi, diantara ribuan orang yang tampil sebagai pahlawan (semu), niscaya suatu saat akan muncul sosok pahlawan sejati. Cuma, pertanyaan yang selalu mengusik kita, kapan ia akan muncul memperbaiki kondisi bangsa kita?***
Oleh Marwanto
(Kedaulatan Rakyat, 11 /11/2008)
Tak ada lencana yang lebih menawan dalam kebudayaan nasional modern daripada monumen-monumen dan makam-makan para tentara yang tak dikenal. Sekalipun makam tersebut menyimpan peninggalan mati yang tak dikenal atau jiwa-jiwa kosong, bagaimanapun makam-makan tersebut telah dipenuhi dengan khayalan nasional yang menghantui.
Paragraf di atas merupakan pendapat Benedict Anderson yang saya kutip dari buku karya Ross Poole, Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme (1993: 119). Lewat pendapat tersebut, tentu Ben Anderson tak sedang memuja seonggok benda mati bernama monumen. Tidak pula memuja kegagahan seorang tentara. Namun satu hal pasti: bagaimanapun epos kepahlawanan telah menjadi salah satu “ruh” dalam episode sejarah sebuah bangsa. Pembicaraan sejarah suatu bangsa tak akan lengkap tanpa membicarakan para pahlawan. Pada akhirnya, sosok pahlawan telah dan selalu menghantui perjalanan sebuah bangsa.
Maka, tak mengherankan jika dalam tiap periode sejarah dari sebuah negara-bangsa, banyak orang ingin tampil sebagai pahlawan. Tentu, seiring dengan perubahan jaman, maka makna dan sosok pahlawan akan selalu mengalami perubahan. Dulu, orang yang disebut pahlawan adalah mereka yang berjasa dalam pertempuran mengusir penjajah atau menghantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan. Lalu, di jaman sekarang ini, siapakah yang pantas disebut pahlawan ?
Tak mudah menjawabnya. Tapi yang pasti, dari dulu hingga sekarang, seorang pahlawan itu berangkat dari nilai. Pahlawan berjuang dan berkorban untuk menegakkan nilai. Nilai apakah yang ingin ditegakkan oleh seorang pahlawan ? Dari orang-orang bijak kita tahu jawabnya adalah nilai keadilan. Perjuangan dan pengorbaan pahlawan berujung pada terciptanya keadilan bagi umat manusia di muka bumi. Atas dasar titik pijak inilah, maka para pahlawan kita di jaman revolusi memperjuangkan kemerdekaan karena --seperti disebutkan dalam preambule konstitusi kita-- penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Jika kita selidiki lebih jauh, sejatinya keadilan sebagai sebuah nilai merupakan muara dari tiga nilai yang dalam kajian moralitas sering disebut sebagai “ide agung”. Prof Mortimer Jerome Adler dalam karyanya yang telah menjadi klasik The Great Ideas: A Syntopicon of Great Book of The Western World, 1952) menguraikan penyelidikannya tentang “ide agung” tersebut. Menurutnya, setidaknya ada tiga ide agung yang menyangga perdaban manusia, yakni: kebenaran, kebaikan dan keindahan. Nah, dengan tergelarnya tiga ide agung tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari maka dapat dipastikan keadilan juga telah maujud dalam kehidupan.
Dari kajian pustaka di atas, maka jika seseorang telah berjuang untuk menegak-kan kebenaran, kabaikan, dan keindahan demi terwujudnya keadilan di muka bumi maka ia sudah bisa disebut sebagai sosok pahlawan. Namun dalam aplikasinya ternyata amat sulit untuk melihat atau menemukan sosok penegak keadilan. Hal ini karena dalam menegakkan keadilan selalu disertai sebuah pertanyaan: keadilan untuk siapa ? Terlebih ketika rasa kebangsaan kita mulai pudar, maka perjuangan untuk menegakkan nilai menjadi amat partikular sifatnya. Dengan kata lain, menegakkan nilai untuk kepentingan bersama sebagai bangsa menjadi sesuatu yang amat mahal dan jarang (untuk tidak menyebut mustahil) untuk diperjuangkan.
Sebagai contoh kecil, seorang yang ingin memberantas kasus korupsi, tapi kebetulan pelakunya itu ada hubungan (entah kerabat atau kolega) dengan yang hendak memberantas maka tentu akan berpikir dua kali. Alih-alih menegakkan keadilan dengan memberantas korupsi, yang terjadi malah berusaha dengan segala cara (baik secara legal maupun kekuatan politik) untuk menghalang-halngi tindak pidana korupsi tersebut.
Alhasil, yang kemudian terjadi adalah munculnya pahlawan-pahlawan bagi suatu kelompok. Padahal, selain berangkat untuk menegakkan nilai, konsep kepahlawanan juga berangkat dari rasa senasib-sepenanggungan. Perjuangan dan pengorbanan tanpa dilandasi rasa senasib-sepenanggungan hanya akan melahirkan heroisme semu. Heroisme semu inilah yang kini sedang melanda kehidupan di tanah air.
Apalagi ketika salah satu buah dari reformasi politik di negeri kita meng-amanatkan jabatan publik dipilih secara langsung oleh rakyat, maka upaya untuk tampil dengan haroisme semu kian menjadi-jadi. Dalam konteks ini, heroisme cuma disepadankan dengan satu kata: popularitas ! Lihatlah, dari pemilihan presiden sampai kepala desa, maka faktor pertama-tama untuk mendulang suara adalah popularitas. Tentu tidak ada salahnya dengan faktor popularitas, namun yang amat disayangkan adalah popularitas itu acapkali sekedar citra (atau ‘tebar pesona”) yang dibuat lewat media massa dan kurang berhubungan dengan kualitas, terlebih kinerja dari seseorang.
Dari realita itulah maka kini sosok pahlawan telah mengalami pendangkalan makna. Sudah pasti pendangkalan makna kepahlawanan ini menerbitkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah sulitnya bangsa ini melakukan perubahan. Ya, karena masing-masing orang hanya mau jadi pahlawan buat kelompoknya atau memikirkan hal-hal yang membuat dirinya supaya tetap populer meski kinerjanya payah.
Di jaman yang serba sulit dimana kohesi sosial kita sebagai bangsa belum sepenuhnya pulih, memang sulit memunculkan sosok pahlawan “sejati”. Pahlawan yang berjuang dan berkorban untuk menegakkan nilai dengan dilandasi rasa senasib-sepenanggungan dan buat kepentingan bersama. Tapi, diantara ribuan orang yang tampil sebagai pahlawan (semu), niscaya suatu saat akan muncul sosok pahlawan sejati. Cuma, pertanyaan yang selalu mengusik kita, kapan ia akan muncul memperbaiki kondisi bangsa kita?***
Langganan:
Postingan (Atom)