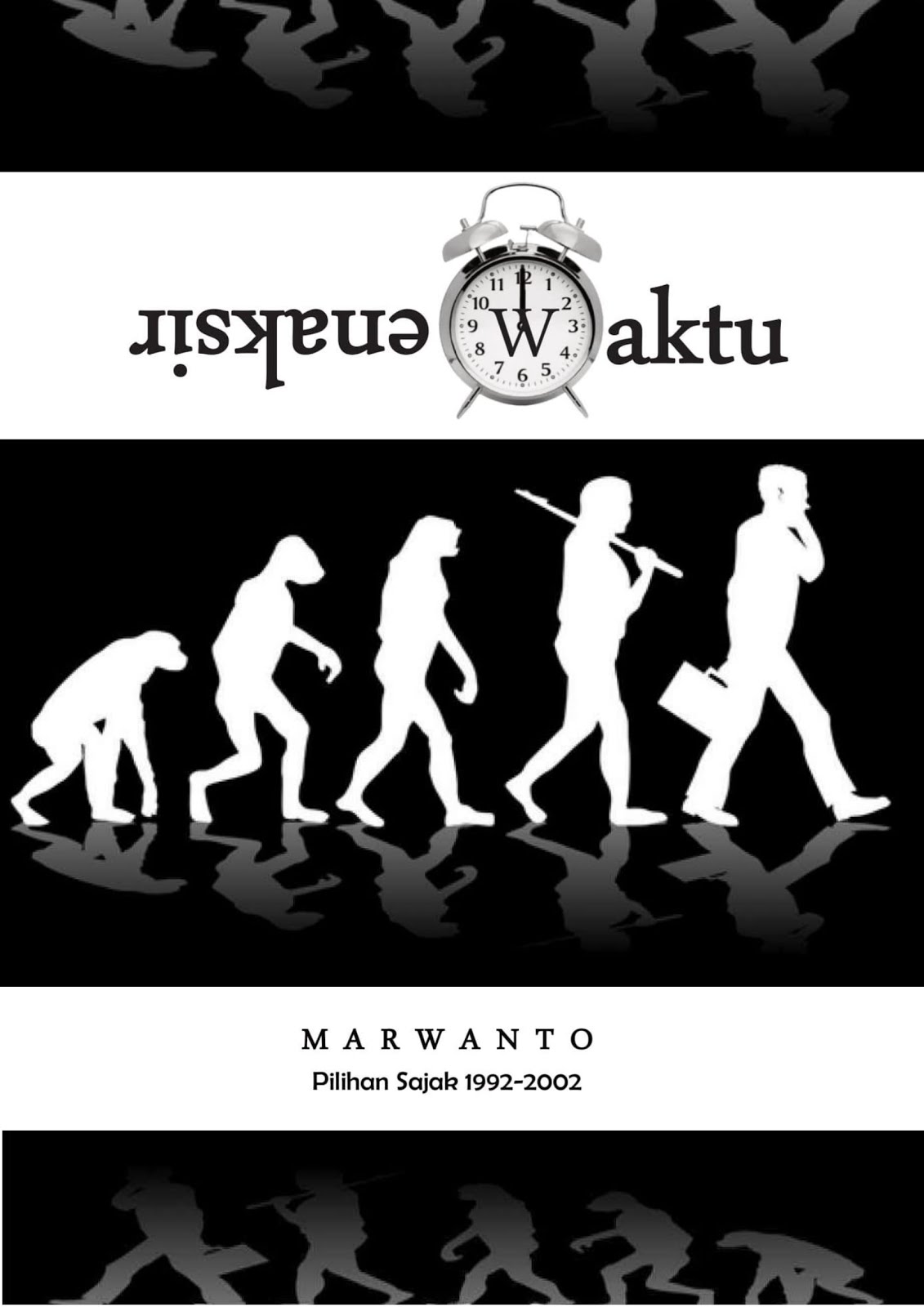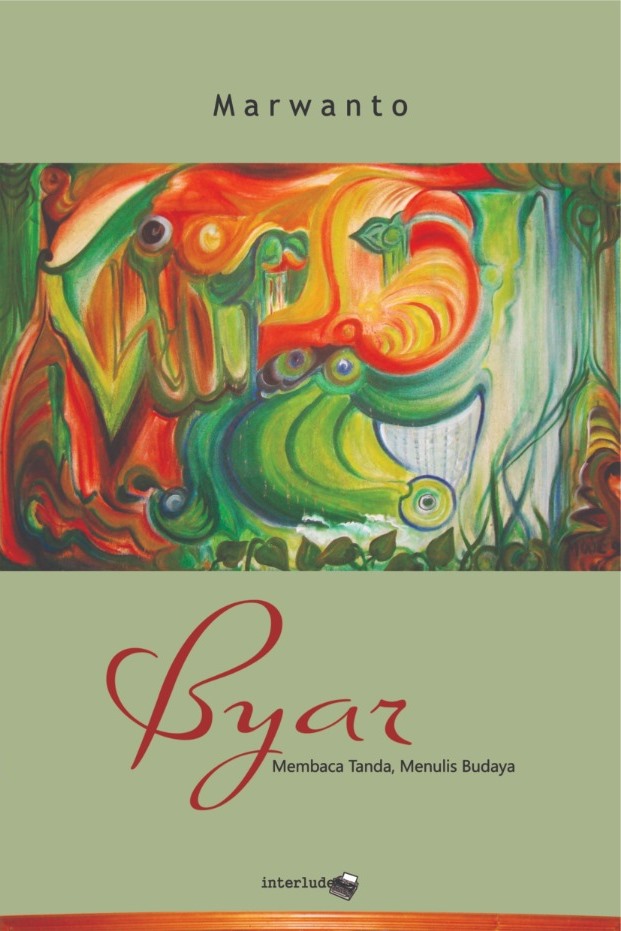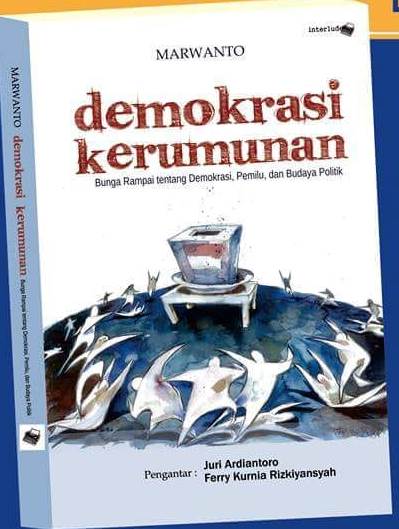Kiai Noor
Kiai Noor Hadi wafat pada malam pencontrengan Pilpres 2009. Saya tidak tahu ia akan memilih pasangan capres nomer berapa, seandainya tanggal 8 Juli itu ia masih sugeng. Setiap saya sowan saat lebaran Idul Fitri, beliau tak pernah mengajak bicara politik. Ia lebih senang ngobrol dan mendiskusikan “radikalisme” pandangan keagamaan.
Namun jangan serta-merta mengidentikan radikalisme yang saya sebut di atas dengan sikap fundamentalisme beragama yang dalam wacana politik, terutama akhir-akhir ini (di tahun melenium yang melelahkan), cenderung memperoleh imej kurang sedap. Konon, radikalisme berasal dari kata “radik” yang berarti akar.
Akar keagamaan (dalam Islam) inilah yang, hemat saya, menjadi titik berangkat pandangan-pandangan Kiai Noor. Karena itulah, bagi orang yang kurang longgar memahami, Kiai Noor sering disalahpahami. Minimal, sebagian orang tak habis pikir mencerna pandangannya. Meski ia Mustaysar PC NU Kulonprogo (dengan demikian tak ada orang yang berani meragukan bahwa ia NU deles) toh ia cukup getol “menyerang” tradisi yang konon paling banyak dilakukan warga nahdliyin: peringatan 7 hari sampai 1000 hari orang meninggal.
Atau, ia adalah orang Muhammadiyah yang ditempatkan di NU? Sebagaimana guyonan selama ini bahwa Mohamad Sobary dan Habib Hirzin adalah orang NU yang ditempatkan di Muhammadiyah? Semua itu tak jadi soal. Seperti yang selalu dipesankan Kiai Noor saat kami (anak-anak muda NU) sowan lebaran di rumahnya: NU atau Muhammadiyah itu hanya wadah. “Jangan sekali-kali kalian memperjuangkan Islam karena NU. Itu salah besar. Perjuangkan agama Islam karena Allah semata !”, demikian yang selalu ia pesankan pada kami.
Pendek kata, “pada tingkat akar” Islam itu satu. Karena sesungguhnya Islam itu memang satu. Ya, inna dinna indallahil Islam, itu. Dan yang satu itu ketika diterjemahkan oleh makhluk menjadi bermacam-macam (interpretasi). Titik krusialnya: jangan sampai “terjemahan” itulah yang kita anggap Islam sebenarnya. Dari sinilah maka wajar jika ada yang menyebut bahwa perilaku beragama umat itu selalu dalam proses (menjadi). Dan tepat pula jika seorang Muhammad Iqbal menulis buku Religion in The Making.
Kini Kiai Noor Hadi, salah satu hamba pilihan Allah (juga aset Kulonprogo) yang selalu mengingatkan akar keagamaan itu telah tiada. Tidak seperti lebaran tahun-tahun lalu, tahun ini saya tak tahu harus sowan kepada siapa untuk memperoleh pencerahan. Benar kata pepatah: “Mati Satu Tumbuh Seribu”. Tapi, dalam konteks ini, ternyata seribu itu hanya angka statistik. Tak mudah mendapati intan diantara hamparan pasir berserakan. Seperti juga belum tentu kita temukan satu puisi pun di sela-sela jutaan sajak yang berjejer di facebook maupun blog-blog pribadi.***
Minggu, 26 Juli 2009
Senin, 06 Juli 2009
OPINI
Tenang, Tenang !, Tenaaannnng !!!
Oleh MARWANTO
Menjelang hari pemungutan suara, saya selalu teringat karikatur karya GM Sudharta yang pernah dimuat harian Kompas sekitar 10 tahun lampau, sesaat sebelum hari coblosan di Pemilu pertama era reformasi.
Dalam karikatur tersebut digambarkan dua orang, dimana yang seorang membisikan kata “tenang” pada telinga orang satunya (gambar 1). Di gambar 2, orang tersebut tak sekedar berbisik, namun sudah berkata pada lawan bicaranya. Hal ini terlihat dari tanda seru dibelakang kata “tenang!” yang menyertai gambar tersebut. Sementara di gambar 3, orang tersebut tak sekedar bicara, tapi berteriak. Hal ini tampak dari gambar mulut orang yang terbuka lebar, dan kata tenang yang menyertai gambar tersebut ditulis: “Tennaaannggg!!!!”.
Hemat saya, karikatur tersebut tak sekedar simpel, tapi benar-benar mengena. Pesan yang hendak disampaikan sangat menohok: pada hari tenang menjelang coblosan (kini contrengan) para kontestan diharapkan menjaga suasana agar kondusif. Tapi? Alih-alih para kontestan menghentikan kegiatan kampanye sehingga membuat suasana bisa menjadi adem-ayem, yang terjadi justru suhu politik menjelang hari H pemungutan suara kian memanas. Makna “tenang” pun berubah menjadi “teriak”.
Filosofi Hari Tenang
Pada Pilpres 2009, KPU menetapkan tanggal 5 sampai 7 Juli sebagai hari tenang. Menurut undang-undang, di hari tenang tidak boleh ada aktivitas kampanye. Jika peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye di hari tenang (baca: di luar jadwal), maka ada sanksi pidana (pasal 213 UU N0. 42 tahun 2008).
Lalu apa sesungguhnya filosofi hari tenang? Mengapa harus ada hari tenang menjelang pemungutan suara? Konon, filosofi hari tenang adalah masa dimana masyarakat benar-benar memperoleh ketenangan untuk dapat berpikir jernih. Berpikir jernih adalah perpaduan antara olah nurani dan logika, sambil mengesampingkan sisi-sisi emosional dalam diri manusia yang sebelumnya diharu-biru oleh gempuran strategi kampanye peserta Pemilu.
Pendek kata, di masa tenang pemilih di harapkan punya waktu untuk merenung. Merenungkan pilihan terbaiknya: semacam ancang-ancang atau masa pengendapan, untuk kemudian menentukan atau memutuskan pilihan. Seperti seorang atlet panah yang akan melepaskan busurnya, butuh jeda beberapa saat untuk konsentrasi.
Atas dasar inilah di hari tenang tak boleh ada aktivitas kampanye. Selain kampanye, rilis dan berita yang memuat hasil survei atau jajak pendapat pun juga dilarang. Sebab, hasil jajak pendapat dapat memengaruhi pendirian pemilih. Menurut teori Bandwagon, seorang pemilih cenderung memutuskan untuk memilih yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Pendek kata, memilih kandidat yang akan menang.
Namun apa yang sekarang terjadi?
Secara formal larangan kampanye memang masih berlaku. Tapi agaknya peserta pemilu kian hari makin canggih membungkus strategi kampanye sehingga di hari tenang pun tetap bisa bergerilya menyasar dan memengaruhi pemilih, tanpa kegiatan tersebut dapat dimasukkan sebagai aktivitas kampanye. Dan, realitas menunjukkan di hari tenang ini justru banyak sekali berkeliaran “teriakan-teriakan” yang mengganggu konsentrasi rakyat untuk merenungkan pilihannya.
Alhasil, hari tenang kenyataannya adalah masa emas bagi peserta Pemilu untuk mendekati pemilih agar meraup dukungan semaksimal mungkin. Konon orang Jawa percaya, seorang yang mencalonkan diri akan menduduki jabatan politik, maka di malam hari pemungutan suara ia dilarang untuk tidur. Kalau ia sampai tertidur (lengah), maka “wahyu” atau “pulung” (keberungtungan) yang telah ia kantongi sangat riskan dicuri orang lain.
“Teriakan” yang Dilegalkan
Demikianlah, pada saat ini hari tenang adalah hari dimana banyak “teriakan” berseliweran. Bahkan karena sejumlah alasan (kebebasan dan keterbukaan, kata orang) “teriakan” di hari tenang itu sekarang ada yang dilegalkan. Rilis berita jajak pendapat atau survei yang semula dilarang di peraturan (pasal 228 UU N0. 42 tahun 2008), kini pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Realitas menunjukkan tak ada lagi beda antara hari tenang atau bukan. Lalu, di mana lagi rakyat mesti mencari makna dan hakekat hari tenang? Atau hari tenang itu memang sudah tak diperlukan lagi?
Oleh MARWANTO
Menjelang hari pemungutan suara, saya selalu teringat karikatur karya GM Sudharta yang pernah dimuat harian Kompas sekitar 10 tahun lampau, sesaat sebelum hari coblosan di Pemilu pertama era reformasi.
Dalam karikatur tersebut digambarkan dua orang, dimana yang seorang membisikan kata “tenang” pada telinga orang satunya (gambar 1). Di gambar 2, orang tersebut tak sekedar berbisik, namun sudah berkata pada lawan bicaranya. Hal ini terlihat dari tanda seru dibelakang kata “tenang!” yang menyertai gambar tersebut. Sementara di gambar 3, orang tersebut tak sekedar bicara, tapi berteriak. Hal ini tampak dari gambar mulut orang yang terbuka lebar, dan kata tenang yang menyertai gambar tersebut ditulis: “Tennaaannggg!!!!”.
Hemat saya, karikatur tersebut tak sekedar simpel, tapi benar-benar mengena. Pesan yang hendak disampaikan sangat menohok: pada hari tenang menjelang coblosan (kini contrengan) para kontestan diharapkan menjaga suasana agar kondusif. Tapi? Alih-alih para kontestan menghentikan kegiatan kampanye sehingga membuat suasana bisa menjadi adem-ayem, yang terjadi justru suhu politik menjelang hari H pemungutan suara kian memanas. Makna “tenang” pun berubah menjadi “teriak”.
Filosofi Hari Tenang
Pada Pilpres 2009, KPU menetapkan tanggal 5 sampai 7 Juli sebagai hari tenang. Menurut undang-undang, di hari tenang tidak boleh ada aktivitas kampanye. Jika peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye di hari tenang (baca: di luar jadwal), maka ada sanksi pidana (pasal 213 UU N0. 42 tahun 2008).
Lalu apa sesungguhnya filosofi hari tenang? Mengapa harus ada hari tenang menjelang pemungutan suara? Konon, filosofi hari tenang adalah masa dimana masyarakat benar-benar memperoleh ketenangan untuk dapat berpikir jernih. Berpikir jernih adalah perpaduan antara olah nurani dan logika, sambil mengesampingkan sisi-sisi emosional dalam diri manusia yang sebelumnya diharu-biru oleh gempuran strategi kampanye peserta Pemilu.
Pendek kata, di masa tenang pemilih di harapkan punya waktu untuk merenung. Merenungkan pilihan terbaiknya: semacam ancang-ancang atau masa pengendapan, untuk kemudian menentukan atau memutuskan pilihan. Seperti seorang atlet panah yang akan melepaskan busurnya, butuh jeda beberapa saat untuk konsentrasi.
Atas dasar inilah di hari tenang tak boleh ada aktivitas kampanye. Selain kampanye, rilis dan berita yang memuat hasil survei atau jajak pendapat pun juga dilarang. Sebab, hasil jajak pendapat dapat memengaruhi pendirian pemilih. Menurut teori Bandwagon, seorang pemilih cenderung memutuskan untuk memilih yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Pendek kata, memilih kandidat yang akan menang.
Namun apa yang sekarang terjadi?
Secara formal larangan kampanye memang masih berlaku. Tapi agaknya peserta pemilu kian hari makin canggih membungkus strategi kampanye sehingga di hari tenang pun tetap bisa bergerilya menyasar dan memengaruhi pemilih, tanpa kegiatan tersebut dapat dimasukkan sebagai aktivitas kampanye. Dan, realitas menunjukkan di hari tenang ini justru banyak sekali berkeliaran “teriakan-teriakan” yang mengganggu konsentrasi rakyat untuk merenungkan pilihannya.
Alhasil, hari tenang kenyataannya adalah masa emas bagi peserta Pemilu untuk mendekati pemilih agar meraup dukungan semaksimal mungkin. Konon orang Jawa percaya, seorang yang mencalonkan diri akan menduduki jabatan politik, maka di malam hari pemungutan suara ia dilarang untuk tidur. Kalau ia sampai tertidur (lengah), maka “wahyu” atau “pulung” (keberungtungan) yang telah ia kantongi sangat riskan dicuri orang lain.
“Teriakan” yang Dilegalkan
Demikianlah, pada saat ini hari tenang adalah hari dimana banyak “teriakan” berseliweran. Bahkan karena sejumlah alasan (kebebasan dan keterbukaan, kata orang) “teriakan” di hari tenang itu sekarang ada yang dilegalkan. Rilis berita jajak pendapat atau survei yang semula dilarang di peraturan (pasal 228 UU N0. 42 tahun 2008), kini pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Realitas menunjukkan tak ada lagi beda antara hari tenang atau bukan. Lalu, di mana lagi rakyat mesti mencari makna dan hakekat hari tenang? Atau hari tenang itu memang sudah tak diperlukan lagi?
Sabtu, 04 Juli 2009
OPINI
Jargon dan Visi Misi
Oleh Marwanto
Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berlaga di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2009) mempunyai jargon atau slogan yang dikenal baik oleh publik. Sebagaimana kita ketahui, jargon ketiga pasangan tersebut adalah: Pro-Rakyat (Megawati-Prabowo), Lanjutkan (SBY-Boediono), dan Lebih Cepat Lebih Baik (Jusuf Kalla-Wiranto).
Menurut sejumlah sumber, jargon diartikan kosakata khusus atau khas yang dipergunakan dalam bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Sementara dalam Tesaurus Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2006), jargon disebut juga patois, slang, atau slogan. Dalam konteks tulisan ini, jargon diartikan kosakata atau rangkaian kosakata yang muncul dari “pemadatan ungkapan” visi-misi yang diusung oleh Pasangan Calon. Dengan pemadatan ungkapan, diharapkan pesan atau isi dari visi-misi dapat diterima dan dimengerti masyarakat dengan lebih mudah atau familiar.
Jargon Pro-Rakyat dari pasangan Mega-Prabowo misalnya, agaknya sudah pas menggambarkan visi-misi yang dibawa Pasangan Calon nomor satu tersebut. Dalam visi-nya, pasangan Mega-Prabowo menyebutkan “Gotong royong membangun kembali Indonesia Raya yang berdaulat, bermartabat, adil dan makmur”. Sementara dari tiga misi pasangan ini, salah satunya menyebutkan: “Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan”.
Sementara jargon Lanjutkan dan Lebih Cepat Lebih Baik, selintas masih kabur untuk menggambarkan visi misi yang diusung kedua Pasangan Calon. Namun karena keduanya bagian dari incumbent, maka mereka mengasumsikan masyarakat telah faham betul visi-misi mereka, terlebih kinerjanya selama ini. Karena itu logis, jika Pasangan Calon nomor 2 dan 3 memilih jargon tersebut.
Jargon Lanjutkan mengajak pemilih untuk melanjutkan visi-misi (bahkan lebih ditekankan pada: melanjutkan capaian atau keberhasilan) dari pemerintah. Sementara Lebih Cepat Lebih Baik mengisyaratkan pencapaian keberhasilan pemerintah mesti dipercepat. Sehingga, meski kedua pasangan ini dilihat dari visi-misi memiliki sejumlah perbedaan (pasangan JK-Wiranto menekankan kemandirian, sebagai counter dari jalannya pemerintahan yang selama ini dinilai kurang mandiri), dari sisi jargon sepertinya tak jauh beda.
Karena jargon mereka tak jauh beda, maka kedua jargon ini bisa saling bertukaran dalam rangka merebut simpati massa. Misalnya ada sejumlah spanduk yang bertuliskan: Cukup Satu Putaran, Lebih Cepat Lebih Baik, Lanjutkan ! Atau: Yang Lebih Cepat dan Lebih Baik, Pantas Melanjutkan Pemerintahan. Akhirnya yang terjadi hanyalah perang jargon.
Perang jargon menjadi pendidikan politik yang kurang baik tatkala rakyat tidak paham betul visi-misi dibalik kandungan jargon tersebut. Apalagi jargon itu semata-mata hanya berangkat dari sebuah strategi untuk menggiring kesadaran massa agar larut dalam suasana tertentu dan jauh dari mencerminkan kristalisasi sebuah visi-misi. Di sisi lain, para kontestan (beserta tim suksesnya) juga tidak berusaha keras untuk mengelaborasi visi-misi mereka, selain mengulang-ulang jargon.
Dalam undang-undang disebutkan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program. Cara menawarkan visi misi dan program yang baik tentu dalam rangka pendidikan politik bagi rakyat. Karena itu idealnya kampanye adalah sebagai salah satu sarana pendidikan politik rakyat. Dengan kampanye, selain memahami hak-hak politiknya, diharapkan rakyat juga mampu berpikir kritis dan sadar betul akan dibawa ke mana arah perjalanan bangsa ini ke depan.
Upaya tersebut hanya akan efektif jika kampanye dilakukan dengan cara atau metode dialogis, dan jauh dari bentuk hiruk-pikuk kampanye yang hanya saling serang jargon dan slogan. Kampanye dialogis, termasuk penyelenggaraan debat Capres dan Cawapres, sebenarnya menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat.
Namun, sebagaimana kita saksikan bersama, pada awalnya debat Capres dan Cawapres berlangsung datar dan dingin. Debat Capres dan Cawapres menjadi sedikit menggelitik saat Jusuf Kalla “menyerang” SBY berulang-kali pada Debat Capres putaran ke-2. (Seyogyanya, pada putaran berikutnya hal ini dilanjutkan dengan elaborasi visi-misi masing-masing calon, dan tak sekedar saling serang dan klaim keberhasilan dalam pemerintahan).
Meski kampanye dengan model dialogis dinilai paling tepat dalam rangka pendidikan politik, bukan berarti jargon itu tidak ada gunanya. Jargon atau slogan yang bersifat “membakar” sangat dibutuhkan pada kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis. Sebab dengan hadirnya jargon yang tepat, akan dapat membangkitkan semangat juang rakyat untuk keluar dari krisis. Dalam konteks ini, jargon berfungsi untuk mencipta momentum politik.
Kini, meski belum sepenuhnya bangkit, masyarakat Indonesia tak bisa lagi disebut berada dalam kubangan krisis. Paling tidak, kita berada pada fase awal kebangkitan. Dan dalam kondisi ini, yang diperlukan tak sekedar jargon. Dalam fase awal kebangkitan, jargon tak akan mampu menciptakan momentum politik, sebab baik pemerintah maupun opisisi berada dalam kondisi yang hampir berimbang (fifty-fifty).
Hemat saya, dalam kondisi sekarang, yang diperlukan adalah mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan kritis tentang arah bangsa ini ke depan. Dan, sekali lagi, elaborasi dari visi-misi Pasangan Calon sangat diperlukan untuk itu. Hal ini selaras dengan jargon Pemilu 2009: Pemilih Cerdas Memilih Pemimpin Berkualitas.***
Oleh Marwanto
Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berlaga di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2009) mempunyai jargon atau slogan yang dikenal baik oleh publik. Sebagaimana kita ketahui, jargon ketiga pasangan tersebut adalah: Pro-Rakyat (Megawati-Prabowo), Lanjutkan (SBY-Boediono), dan Lebih Cepat Lebih Baik (Jusuf Kalla-Wiranto).
Menurut sejumlah sumber, jargon diartikan kosakata khusus atau khas yang dipergunakan dalam bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Sementara dalam Tesaurus Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2006), jargon disebut juga patois, slang, atau slogan. Dalam konteks tulisan ini, jargon diartikan kosakata atau rangkaian kosakata yang muncul dari “pemadatan ungkapan” visi-misi yang diusung oleh Pasangan Calon. Dengan pemadatan ungkapan, diharapkan pesan atau isi dari visi-misi dapat diterima dan dimengerti masyarakat dengan lebih mudah atau familiar.
Jargon Pro-Rakyat dari pasangan Mega-Prabowo misalnya, agaknya sudah pas menggambarkan visi-misi yang dibawa Pasangan Calon nomor satu tersebut. Dalam visi-nya, pasangan Mega-Prabowo menyebutkan “Gotong royong membangun kembali Indonesia Raya yang berdaulat, bermartabat, adil dan makmur”. Sementara dari tiga misi pasangan ini, salah satunya menyebutkan: “Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan”.
Sementara jargon Lanjutkan dan Lebih Cepat Lebih Baik, selintas masih kabur untuk menggambarkan visi misi yang diusung kedua Pasangan Calon. Namun karena keduanya bagian dari incumbent, maka mereka mengasumsikan masyarakat telah faham betul visi-misi mereka, terlebih kinerjanya selama ini. Karena itu logis, jika Pasangan Calon nomor 2 dan 3 memilih jargon tersebut.
Jargon Lanjutkan mengajak pemilih untuk melanjutkan visi-misi (bahkan lebih ditekankan pada: melanjutkan capaian atau keberhasilan) dari pemerintah. Sementara Lebih Cepat Lebih Baik mengisyaratkan pencapaian keberhasilan pemerintah mesti dipercepat. Sehingga, meski kedua pasangan ini dilihat dari visi-misi memiliki sejumlah perbedaan (pasangan JK-Wiranto menekankan kemandirian, sebagai counter dari jalannya pemerintahan yang selama ini dinilai kurang mandiri), dari sisi jargon sepertinya tak jauh beda.
Karena jargon mereka tak jauh beda, maka kedua jargon ini bisa saling bertukaran dalam rangka merebut simpati massa. Misalnya ada sejumlah spanduk yang bertuliskan: Cukup Satu Putaran, Lebih Cepat Lebih Baik, Lanjutkan ! Atau: Yang Lebih Cepat dan Lebih Baik, Pantas Melanjutkan Pemerintahan. Akhirnya yang terjadi hanyalah perang jargon.
Perang jargon menjadi pendidikan politik yang kurang baik tatkala rakyat tidak paham betul visi-misi dibalik kandungan jargon tersebut. Apalagi jargon itu semata-mata hanya berangkat dari sebuah strategi untuk menggiring kesadaran massa agar larut dalam suasana tertentu dan jauh dari mencerminkan kristalisasi sebuah visi-misi. Di sisi lain, para kontestan (beserta tim suksesnya) juga tidak berusaha keras untuk mengelaborasi visi-misi mereka, selain mengulang-ulang jargon.
Dalam undang-undang disebutkan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program. Cara menawarkan visi misi dan program yang baik tentu dalam rangka pendidikan politik bagi rakyat. Karena itu idealnya kampanye adalah sebagai salah satu sarana pendidikan politik rakyat. Dengan kampanye, selain memahami hak-hak politiknya, diharapkan rakyat juga mampu berpikir kritis dan sadar betul akan dibawa ke mana arah perjalanan bangsa ini ke depan.
Upaya tersebut hanya akan efektif jika kampanye dilakukan dengan cara atau metode dialogis, dan jauh dari bentuk hiruk-pikuk kampanye yang hanya saling serang jargon dan slogan. Kampanye dialogis, termasuk penyelenggaraan debat Capres dan Cawapres, sebenarnya menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat.
Namun, sebagaimana kita saksikan bersama, pada awalnya debat Capres dan Cawapres berlangsung datar dan dingin. Debat Capres dan Cawapres menjadi sedikit menggelitik saat Jusuf Kalla “menyerang” SBY berulang-kali pada Debat Capres putaran ke-2. (Seyogyanya, pada putaran berikutnya hal ini dilanjutkan dengan elaborasi visi-misi masing-masing calon, dan tak sekedar saling serang dan klaim keberhasilan dalam pemerintahan).
Meski kampanye dengan model dialogis dinilai paling tepat dalam rangka pendidikan politik, bukan berarti jargon itu tidak ada gunanya. Jargon atau slogan yang bersifat “membakar” sangat dibutuhkan pada kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis. Sebab dengan hadirnya jargon yang tepat, akan dapat membangkitkan semangat juang rakyat untuk keluar dari krisis. Dalam konteks ini, jargon berfungsi untuk mencipta momentum politik.
Kini, meski belum sepenuhnya bangkit, masyarakat Indonesia tak bisa lagi disebut berada dalam kubangan krisis. Paling tidak, kita berada pada fase awal kebangkitan. Dan dalam kondisi ini, yang diperlukan tak sekedar jargon. Dalam fase awal kebangkitan, jargon tak akan mampu menciptakan momentum politik, sebab baik pemerintah maupun opisisi berada dalam kondisi yang hampir berimbang (fifty-fifty).
Hemat saya, dalam kondisi sekarang, yang diperlukan adalah mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan kritis tentang arah bangsa ini ke depan. Dan, sekali lagi, elaborasi dari visi-misi Pasangan Calon sangat diperlukan untuk itu. Hal ini selaras dengan jargon Pemilu 2009: Pemilih Cerdas Memilih Pemimpin Berkualitas.***
Langganan:
Postingan (Atom)