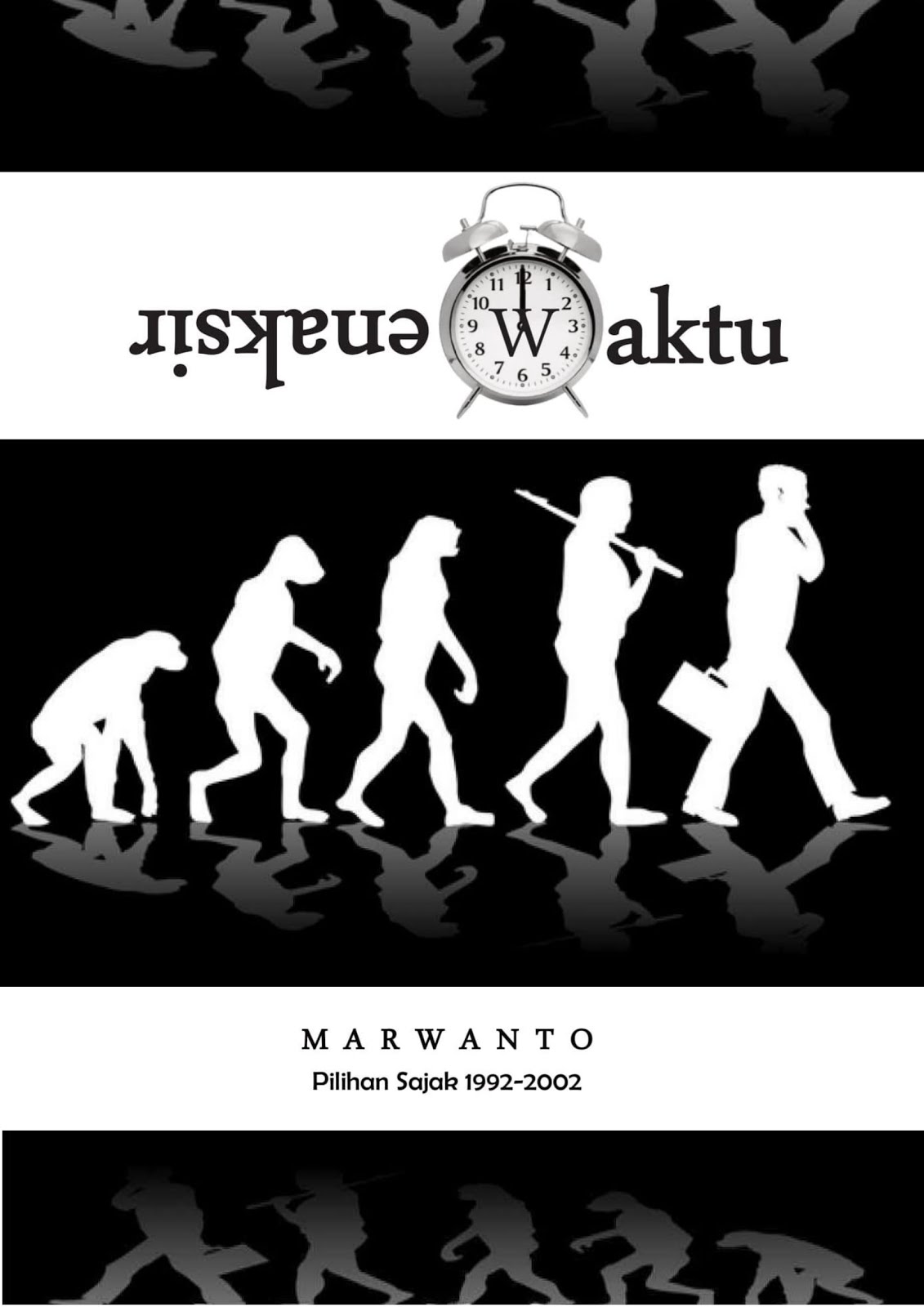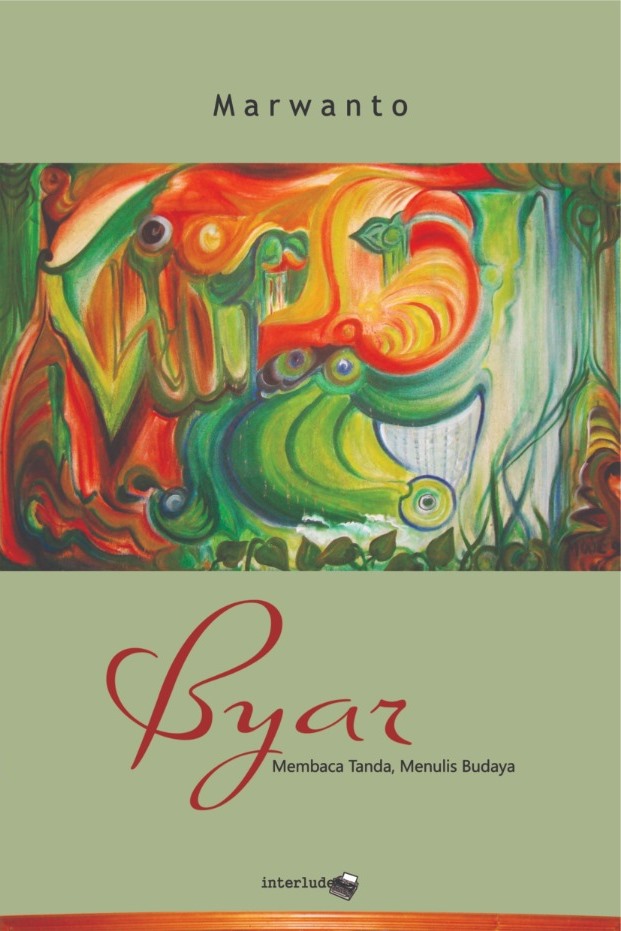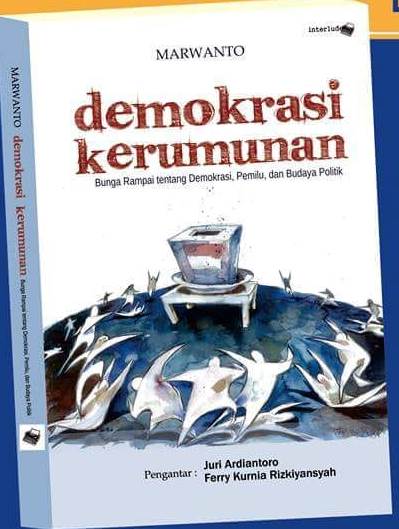Oposisi Tak Diperlukan Lagi ?
Oleh MARWANTO
(Dimuat Harian Jogja, 17 Oktober 2009)
Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 segera akan dilantik 20 Oktober mendatang. Kemenangan pasangan calon SBY-Boediono sudah diprediksi sejumlah pihak –baik pengamat, lembaga survei maupun masyarakat awam sekalipun. Hasil Pilpres 2009 pun menjadi kurang menarik untuk diikuti. Justru yang paling menarik perhatian orang dari Pilpres 2009 waktu itu adalah apakah Pilpres akan berlangsung dua atau satu putaran. Dan seperti kita saksikan bersama, Pilpres 2009 memang hanya berlangsung satu putaran.
Meski Pilpres 2009 sudah berlangsung dan kurang menarik diikuti, hemat saya ada satu hal yang patut ditelaah kaitannya dengan perolehan suara ketiga pasangan calon. Dari ketiga perolehan suara pasangan calon, hanya pasangan JK-Wiranto yang diluar dugaan. Menurut sejumlah lembaga survei, elektabilitas pasangan ini meningkat mendekati hari H pemilu dan diperkirakan akan head to head dengan pasangan SBY-Boediono jika Pilpres berlangsung dua putaran.
Peran partai memang tidak lagi signifikan untuk mendulang suara dalam Pilpres. Namun pasangan JK-Wiranto dikenal mempunyai jaringan luas –baik di Jawa maupun luar Jawa. Jangan lupa, pasangan JK-Wiranto juga didukung sejumlah tokoh ormas keagamaan. Tapi mengapa perolehan suara mereka jeblok?
Mari kita telusuri dari karakteristik perilaku pemilih. Berkaca dari hasil Pemilu Legislatif 2009, masyarakat kita mendasarkan pilihannya lebih menggunakan pertimbangan faktor rasional daripada ideologis. Pendek kata, pemilih kian pragmatis. Sehingga, faktor ideologis tak lagi menjadi pertimbangan yang dominan bagi pemilih kita. Konon, PKS memperoleh simpati (meningkat perolehan suaranya) bukan lantaran faktor ideologis, tapi partai ini mampu membangun citra sebagai partai yang bersih dan peduli.
Di Pilpres 2009 (karena pasangan calon yang terbatas), selain perilaku pemilih yang pragmatis, notabene pemilih kita hanya terbagi dalam dua arus besar: yakni pendukung pemerintah dan yang di luar pemerintah (baca: opisisi). Dilihat dari cara pandang ini, peta dua pasangan sudah jelas: pasangan Mega-Prabowo mewakili oposisi, sementara dari pemerintah (baca: incumbent) diwakili pasangan SBY-Boediono.
Lalu pasangan JK-Wiranto? Pasangan ini tidak jelas benar posisinya. Di satu sisi, JK acapkali ditempatkan sebagai bagian dari pemerintah. Namun dalam berbagai kesempatan (kampanye), JK sering mengkritik SBY. Sebagai bagian dari (keberhasilan) pemerintahan, posisi JK berada di bawah bayang-bayang SBY. Masyarakat awam menilai, keberhasilan pemerintahan karena peran presiden (SBY), dan bukan JK (wakil presiden). Di lain pihak, sebagai pengritik SBY, posisinya kalah dibanding oposisi (pasangan Mega-Prabowo).
Alhasil, ditilik dari dua kutub besar perilaku pemilih Pilpres 2009 (mendukung pemerintah atau oposisi), pasangan JK-Wiranto logis jika hanya memperoleh suara yang kecil. Agaknya, masyarakat menginginkan suatu sikap yang tegas dari politisi: pemerintah atau oposisi. Wilayah “abu-abu” atau permainan “dua kaki” yang dilakukan JK (dan partai Golkar dalam lima tahun terakhir), ternyata tak mendapat simpati rakyat.
Justru, masyarakat masih menaruh respek dan hormat pada opoisisi (pasangan Mega-Prabowo). Gabungan partai yang mengusung pasangan Mega-Prabowo di Pileg kemarin memperoleh suara pada kisaran 21%, tapi dalam Pilpres justru suaranya meningkat menjadi sekitar 26,79%. Sedang gabungan partai yang mengusung JK-Wiranto di Pileg memperoleh suara sekitar 22% namun suara mereka pada Pilpres menurun jauh hanya sekitar 12,41%.
Respek masyarakat terhadap oposisi bisa jadi didasarkan atas asumsi akan adanya perubahan kondisi kehidupan yang lebih baik, bukan sekedar melanjutkan. Dan setiap oposisi memang lahir dari ide perubahan. Dari sini sejatinya oposisi dapat memperoleh simpati dari rakyat. Tinggal bagaimana parpol yang menjadi oposisi itu merebutnya (baca: menciptakan momentum).
Namun menjadi oposisi di negeri ini memang butuh keberanian. Dua partai besar (Golkar dan PDIP) yang nyata-nyata menjadi rival partai pendukung presiden terpilih pada Pilpres 2009, bisa jadi akan memilih “jalan aman” (baca: bergabung dengan pemerintahan SBY). Padahal, baik Golkar dan PDIP adalah partai lama dengan kelebihan masing-masing. Golkar punya SDM pengurus yang bagus hingga tingkat bawah. Sementara PDIP punya pendukung fanatik yang cukup besar.
Namun memang realitas menunjukkan belum ada dalam sejarah politik di Indonesia partai oposisi itu mampu besar secara langgeng. Kebetulan, PDIP yang baru satu periode pemerintahan menjadi oposisi suaranya merosot. Namun, kata teori politik, jika sebuah kekuasaan tidak ada penyeimbangnya, maka yang akan muncul bukanlah pemerintahan yang kuat, tapi pemerintahan yang otoriter. Sehingga oposisi menjadi salah satu pra syarat terpeliharanya iklim kehidupan kenegaraan yang demokratis.
Lalu, siapa yang akan berani tampil sebagai oposisi demi mengemban visi luhur melakukan chek and balances agar tak lahir kekuasaan yang otoriter? Politisi kita lebih memilih oposisi demi kesehatan demokrasi atau kursi (di kabinet) ? Atau, format politik di negeri ini sedang akan bergeser: pemerintahan SBY akan merangkul semua kekuatan politik sehingga fungsi parlemen kembali seperti rezim Soeharto sekedar sebagai stempel pemerintah ? Lalu gerakan oposisi kembali diperankan oleh media maupun LSM dalam wujudnya oposisi ekstra-parlementer? Kita tunggu saja.***
Selasa, 20 Oktober 2009
Langganan:
Postingan (Atom)