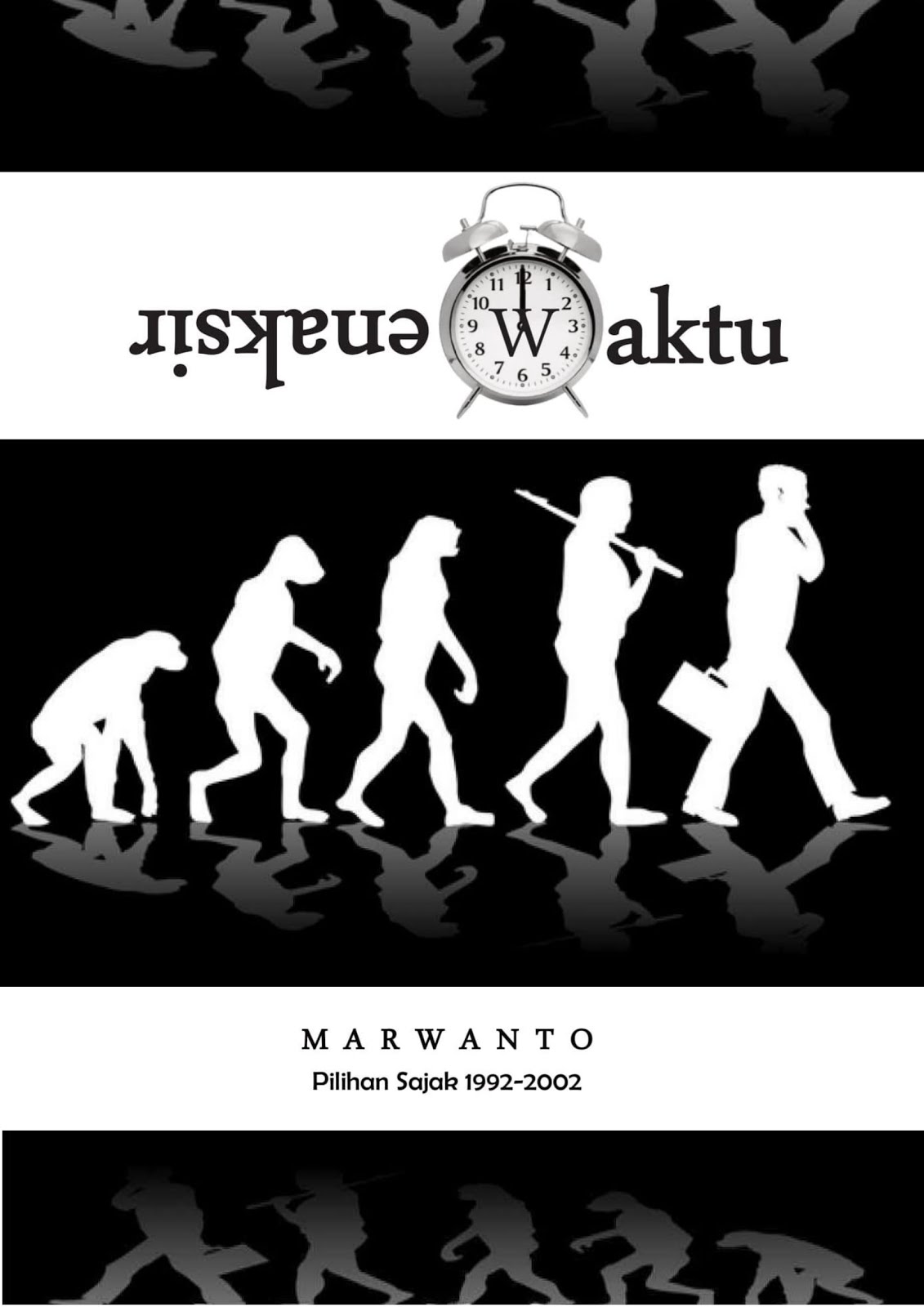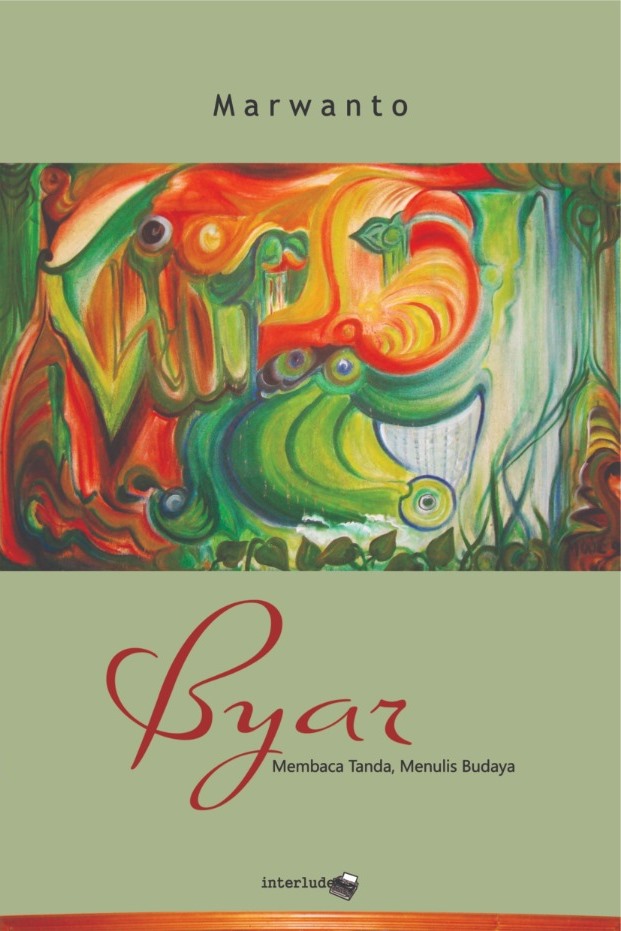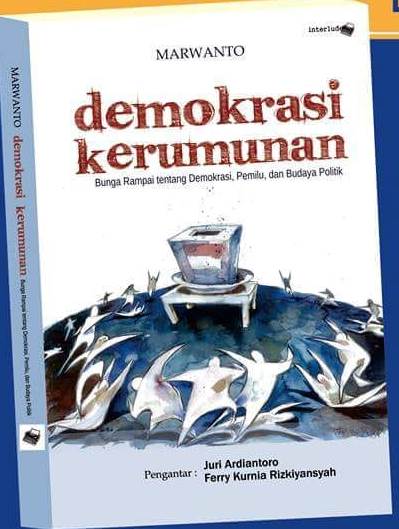Golput ( Tak Pernah ) Menang
Oleh MARWANTO
("Harian Jogja", 25 Juni 2009)
Pemilu adalah sandiwara belaka...
Demikian keyakinan dr. Noguera, tokoh rekaan Gabriel Garcia Marques dalam novelnya One Hundred Years of Solitude (Seratus Tahun Kesunyian). Saya selalu membayangkan keyakinan dr. Noguera tersebut dengan pelaksanaan Pemilu di era Orde Baru (Orba). Pemilu yang penuh rekayasa. Dimana penyelenggara Pemilu dengan berbagai cara berusaha mendesain agar hasil Pemilu selalu dimenangkan oleh partai yang sedang berkuasa (“partai pemerintah”).
Desain penguasa untuk memenangkan salah satu kontestan Pemilu dilakukan mulai dari soal kebijakan sampai masalah teknis. Dalam hal kebijakan, misalnya, penguasa Orba membuat aturan bahwa kepengurusan partai politik tidak diperbolehkan sampai tingkat akar rumput. Intinya, di satu sisi rakyat bawah tidak diberi kesempatan untuk berpolitik, sementara di sisi lain aparat birokrasi dari atas sampai bawah dijadikan kader (atau minimal diwajibkan mendukung) salah satu peserta Pemilu.
Tak pelak, waktu itu Pemilu memang hanya sandiwara: penguasa bertindak sebagai penulis naskah sekaligus sutradara, dengan pemain yang sama sekali tidak memiliki otonomi untuk berbuat selalin yang telah digariskan sang sutradara. Sehingga, meski belum ada tren quick-count, hasil Pemilu sudah bisa diketahui sejak dini. Pemilu sekedar seremonial lima tahunan bangsa Indonesia, untuk “menghormati dinamika politik yang remeh-temeh”: misal momentum Pak Harto mengganti wakil presiden.
Ketika Pemilu hanya dibuat main-main atau sandiwara, layak jika sebagian masyarakat mengkritiknya. Kritik itu dialamatkan untuk membenahi agar pelaksanaan Pemilu berlangsung demokratis, luber, dan jurdil. Sikap kritis yang tak kunjung direspon penguasa dengan memperbaiki pelaksanaan Pemilu itu kemudian maujud menjadi gerakan golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih. Dalam konteks ini, golput adalah pilihan politik yang didasari atas sejumlah kekecewaan terhadap praktik politik waktu itu.
Dari sisi kuantitas, golput di era Orba amat kecil (atau karena “desain dari penguasa” sehingga data riil tentang Golput waktu itu tidak pernah terpublikasi secara jujur ?). Namun sejak dulu golput memang sudah bikin risih dan resah. Bahkan rezim Soeharto amat peka (dan dalam taraf tertentu “takut” sehingga acapkali harus bertindak represif) terhadap orang seperti Arief Budiman --tokoh yang sering dipandang sebagai penggerak golput.
Meski bikin risih dan resah penguasa, golput di era Orba sebenarnya tak pernah menang. Dalam arti, gerakan golput tak pernah berhasil mengubah mekanisme Pemilu (dan sistem politik secara umum) di negeri ini menjadi lebih demokratis. Berubahnya tatacara pelaksanaan Pemilu yang lebih demokratis, luber dan jurdil bukan buah dari golput, namun akibat gerakan reformasi tahun 1998. Reformasi 1998 yang menuntut perubahan tatakelola kehidupan kenegaraan di segala bidang, salah satunya berhasil menggelar Pemilu 1999 –Pemilu yang oleh sebagian pengamat dari sisi demokratis dan luber jurdil-nya sering disepadankan Pemilu 1955.
Pada Pemilu 1999 orang tak lagi bicara tentang golput. Sebab kran keterbukaan telah dibuka lebar, sebagai lawan dari sikap represif penguasa yang sebelumnya menjadi salah satu penyebab golput. Ada euforia politik waktu itu, yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu. Tercatat, pada Pemilu 1999 persentase voter turn-out (pemilih yang menggunakan hak pilihnya) sekitar 92%. Bahkan menurut saya, partisipasi pemilih pada waktu itu seharusnya bisa lebih tinggi lagi, mendekati 100%. Mengapa?
Karena pada Pemilu 1999 saya menjadi Gastarlih (Petugas Pendaftaran Pemilih), maka masih bening dalam ingatan saya tentang model pendaftaran pemilih waktu itu. Yakni, diumumkan pada masyarakat bahwa tanggal sekian akan ada pendaftaran pemilih. Selanjutnya pada tanggal yang sudah ditentukan, Gastarlih bertindak pasif: hanya duduk menunggu pemilih yang datang mendaftarkan diri. Gastarlih dilarang aktif mendaftar pemilih, dengan alasan karena trauma rezim Orba dimana penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari birokrasi sering memobilisir warga. Artinya, pemilih yang datang minta didaftar jelas yang berniat akan menggunakan hak pilihnya di Pemilu. Tapi, tidak ada yang mempersoalkan apakah pemilih yang minta didaftar itu secara persentase sudah tinggi jika dilihat dari jumlah penduduk yang telah punya hak pilih.
Dari cara Gastarlih yang pasif tadi, sebenarnya bisa menjaring partisipasi pemilih yang genuine (murni). Namun model pendaftaran pemilih seperti itu diubah pada Pemilu 2004 dengan dibentuknya Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih). Beda dengan Gastarlih, Pantarlih bertindak aktif: terjun ke lapangan untuk mendata penduduk (secara de fakto) yang telah punya hak pilih. Dibanding Pemilu 1999, persentase pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu 2004 turun menjadi 84%. Penurunan ini bisa karena beralihnya model pendaftaran pemilih atau karena faktor politis (rakyat kecewa dengan kinerja elit politik pada fase pertama ere reformasi). Yang pasti: dari sekitar 16% golput tersebut tak ada yang disebabkan ghost-voter (pemilih yang hanya ada dalam daftar tapi tak ada di kenyataan).
Pemilu 2009 menggunakan pendekatan de jure untuk pendataan pemilih. Model ini berpotensi memperbesar jumlah ghost-voter, di satu sisi karena tingkat mobilitas masyarakat kita sudah tinggi dan di saat yang sama tidak dibarengi kualitas administrasi kependudukan yang baik. Tentu kisruh DPT tak hanya disebabkan faktor ini. Namun tingginya golput Pileg 2009 tak bisa disebut pemenang. Baik dari aspek kualitas: yang mempersoalkan golput Pileg tetap mengikuti Pilpres, demikian juga kongres golput tak bisa mengurangi antusias masyarakat pada Pemilu. Pun kuantitas: angka golput tak semestinya dibandingkan dengan perolehan partai A atau B. Angka golput (49.677.076) logikanya dihadapkan dengan pemilih yang menggunakan hak pilih (121.588.366) atau angka golput plus suara tidak sah pun jika digabung (67.165.657) belum bisa mengalahkan suara sah (104. 099.785).
Sejak era reformasi 1998 Pemilu di negera kita tak lagi sandiwara. Kalaupun ada kekuarangan di sana-sini, mari benahi bersama !***
Sabtu, 27 Juni 2009
Langganan:
Postingan (Atom)