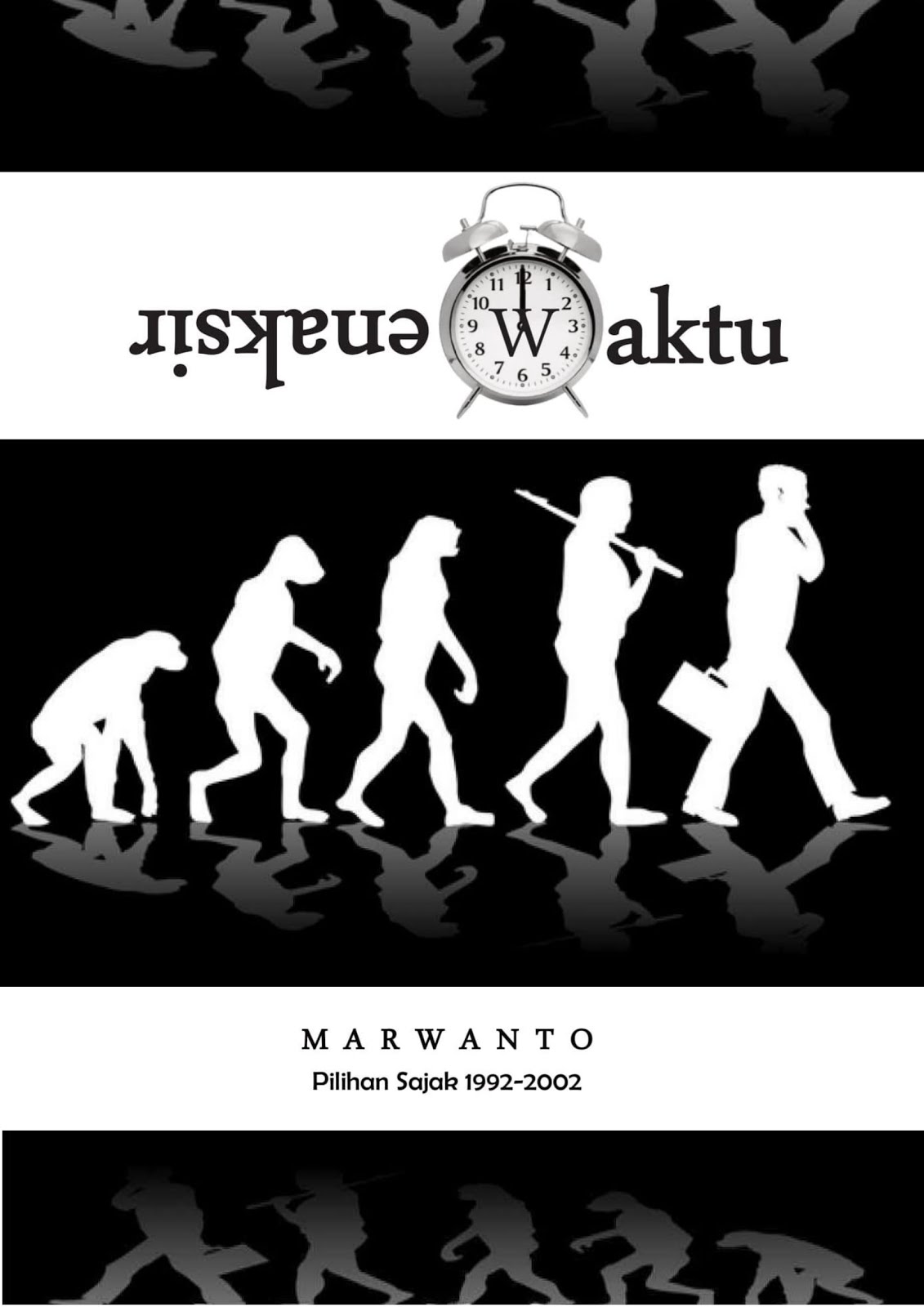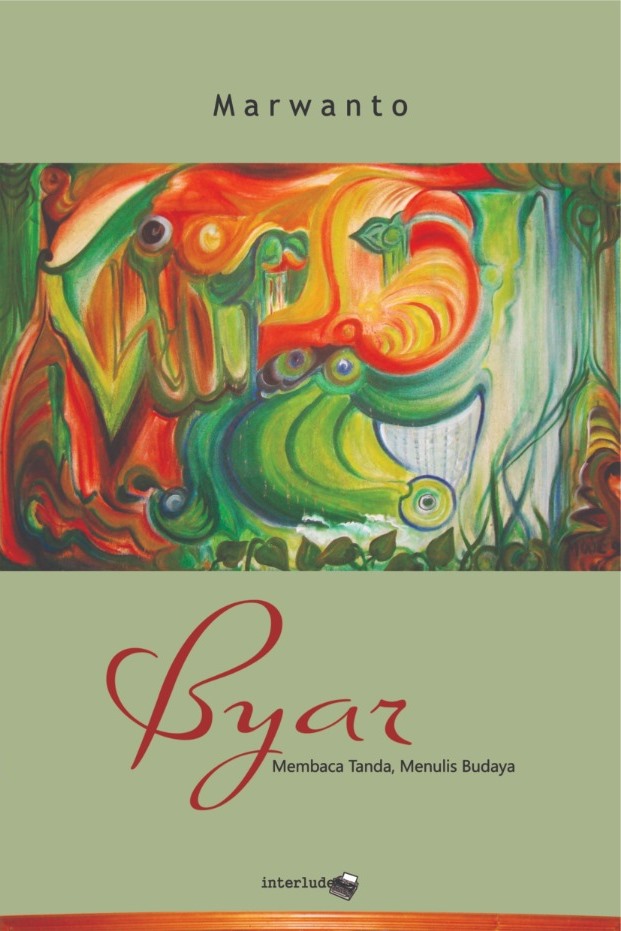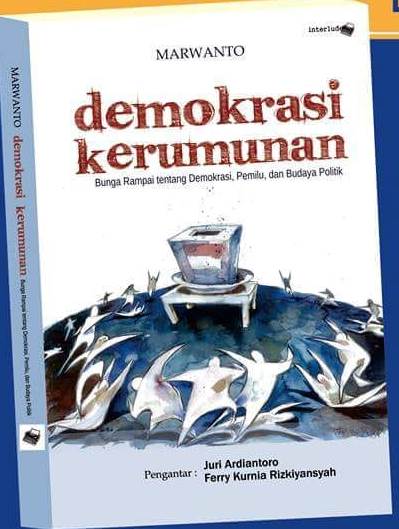Demokrasi Kerumunan
Oleh MARWANTO
(Dimuat Harian KOMPAS hlm Yogya-Jateng, 15 Maret 2010)
Seiring maraknya praktik demokrasi elektoral (Pemilu, Pemilukada, serta Pilkades), gugatan atas kriteria pemilih pun dilontarkan. Hal ini didasari atas argumentasi bahwa demokrasi yang menerapkan mekanisme pemilihan langsung kurang menjamin munculnya wakil rakyat dan pemimpin berkualitas. Bagaimana bisa kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh pilihan publik dengan perolehan suara terbanyak?
Konon, pada zaman Yunani kuno praktik berdemokrasi (termasuk pemilu), hanya melibatkan apa yang disebut sebagai “warga negara resmi”. Rakyat jelata, atau lebih tepatnya budak, tidak diikutkan dalam pemilu. Demokrasi Yunani kuno beranggapan masalah politik kenegaraan lebih tepat jika diputuskan oleh orang-orang yang memiliki pandangan tentang kebajikan hidup.
Mirip hal tersebut, dulu di berbagai wilayah tanah air saat melangsungkan pemilihan pemimpin adat acapkali dilakukan dalam sebuah rembug (musyawarah) yang dihadiri oleh utusan tokoh-tokoh masyarakat. Sementara di era Orde Baru, kita tahu, mekanisme demokrasi perwakilan ini dipraktikkan MPR untuk memilih presiden dan DPRD untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota).
Gelombang demokratisasi awal abad 21 ternyata membawa tren mekanisme pemilihan langsung. Demokrasi perwakilan dianggap bias (bahkan gagal), karena wakil rakyat di parlemen yang diharapkan memperjuangkan aspirasi warga malah berkiblat pada kepentingan partai politik. Oligarki parpol ini membuat pemilihan pemimpin tak lebih sebagai praktik dagang sapi para elit parpol.
Namun ketika hasil pemilihan langsung tak juga kunjung berkorelasi positif dengan kesejahteraan, maka yang kemudian muncul tidak saja polemik seputar mekanisme pemilihan, tapi juga filosofi yang mendasari definisi pemilih (warga yang dilibatkan pemilu). Pihak yang setuju “membatasi” pemilih atau mendukung mekanisme pemilihan tidak langsung (perwakilan) memiliki argumentasi berikut.
Pertama, warga yang terlibat proses pemilu pada hakekatnya menanggung sejumlah konsekuensi. Diantaranya konsekuensi terhadap pilihannya. Lebih jauh lagi, konsekuensi terhadap kekuasaan yang terbentuk dari hasil pemilu. Artinya, warga sebagai pemilih semestinya juga terlibat aktif mengawasi pemerintahan hasil pemilu. Konsekuensi ini sangat berat jika ditanggung warga negara biasa, apalagi budak.
Kedua, membatasi keterlibatan warga dapat menekan biaya pelaksanaan pemilu. Ditengah citra mahalnya biaya demokrasi hal ini menjadi relevan. Dengan kata lain, pelaksanaan pemilu yang berbiaya rendah dan berlangsung efisien-efektif, sekaligus sudah mampu melahirkan kekuasaan legitimet yang mengemban amanat konstituen dalam rangka menyejahterakan rakyat.
Ketiga, hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Karena pemilih adalah warga terdidik (cerdas), maka selain persentase suara tidak sah sedikit, pilihan mereka juga diharapkan menghasilkan wakil rakyat (pemimpin) yang berkualitas. Pemilu 2009 di negera kita, yang punya slogan: pemilih cerdas memilih wakil berkualitas, agaknya terinspirasi dari sini.
Sementara mereka yang tidak setuju “pembatasan” pemilih akan berdalih bahwa hak pilih itu seharusnya berlaku universal. Semua warga negara –tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis—seharusnya berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pengakuan hak pilih universal ini menjadi salah satu syarat sebuah pemilu yang demokratis (Eep Saifullah Fatah, 1998: 101).
Dua pandangan tersebut tidak seharusnya diposisikan berhadapan secara diametral dan kaku. Praktik pemilu di zaman Yunani kuno yang mengharuskan pemilih adalah “warga negara resmi” mesti dimaknai bahwa pemilih dalam pemilu haruslah warga bangsa yang terdidik. Untuk itu pendidikan pemilih diharapkan menjadi ruh bagi penyelenggaraan pemilu.
Pendidikan pemilih merupakan agenda kepemiluan yang berlangsung terus menerus. Selain itu pendidikan pemilih adalah agenda yang terintegrasi sehingga bisa berdampak efektif dalam rangka melahirkan pemilih cerdas dan bertanggung jawab yang pada akhirnya dari pilihan mereka muncul pemimpin (wakil rakyat) berkualitas.
Makna integral pendidikan pemilih tidak saja dilihat dari aspek pelaku bahwa perlu menciptakan sinergisitas antara penyelenggara (KPU), pemerintah, partai politik dan stake-holder (pemangku kepentingan). Lebih dari itu, pendidikan pemilih semestinya diletakkan menjadi bagian pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas. Sebuah upaya untuk menumbuhkan kesadaran warga bangsa mengenai aspek-aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Disamping pendidikan pemilih, agenda dalam rangka pembenahan kualitas praktik demokrasi elektoral juga perlu dari sisi kontestan pemilu. Secerdas apapun rakyat (pemilih), tidak akan ada artinya jika pemilu hanya diikuti oleh kontestan yang hanya menebar popularitas dan menomorsatukan kekuatan finansial, bukan kontestan yang mengandalkan aspek moralitas, integritas dan kualitas personal.
Agenda ini tidak hanya dalam rangka menyiapkan pemilih berkualitas menyongsong Pemilu 2014 dan pemilukada di sejumlah daerah. Bukan pula hanya untuk mendongkrak partisipasi pemilih yang terus menurun. Tapi sebuah agenda mendasar dalam rangka menyelamatkan pemilu. Agar mekanisme pemilihan langsung tidak hanya menghasilkan “demokrasi kerumuman”: asal besar dan banyak maka terpilih.
Demokrasi kerumunan harus kita cegah mulai hari ini. Sebab prinsip asal besar dan banyak maka terpilih (menang) sejatinya telah mendistorsi esensi demokrasi.
Senin, 05 April 2010
Langganan:
Postingan (Atom)