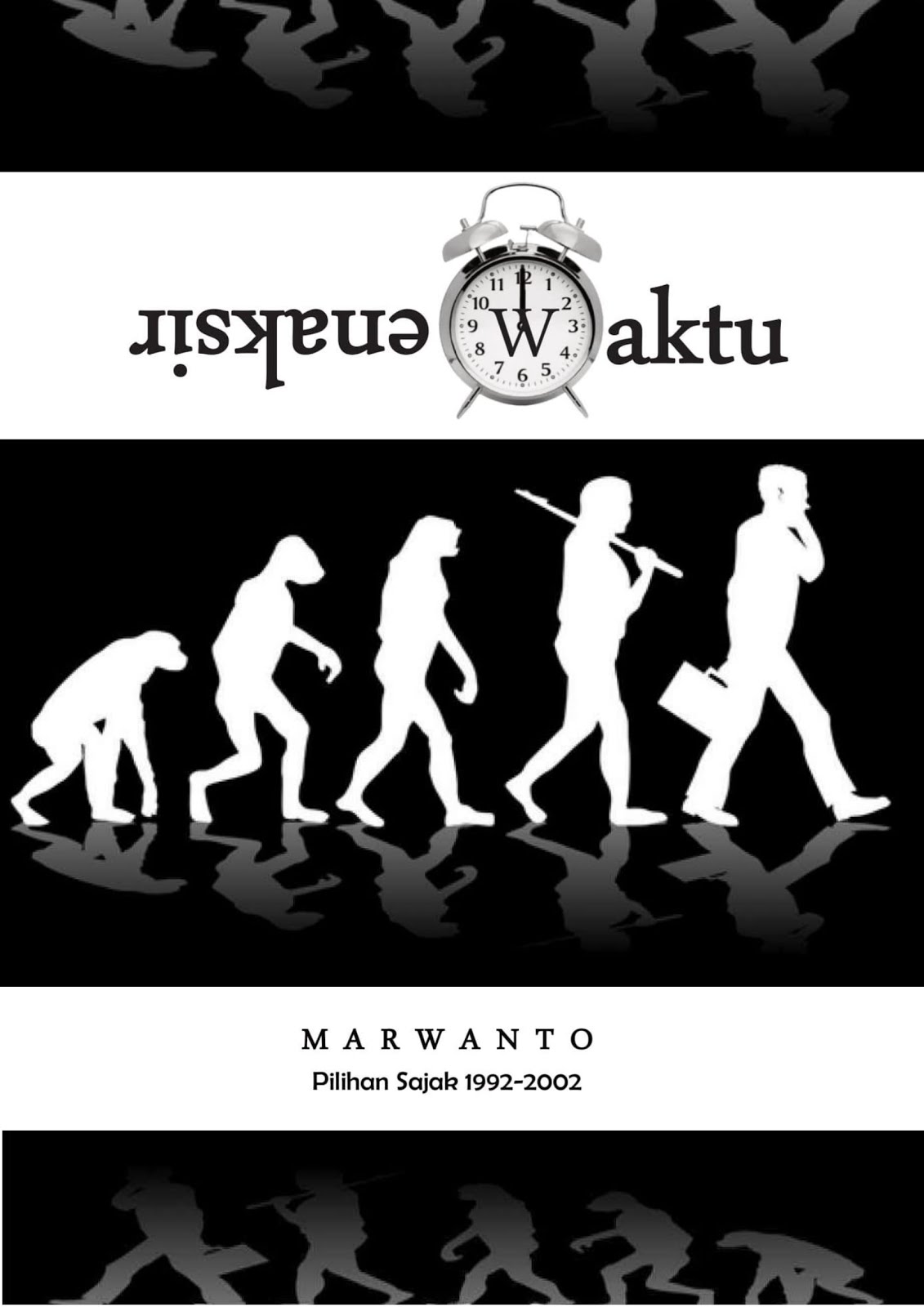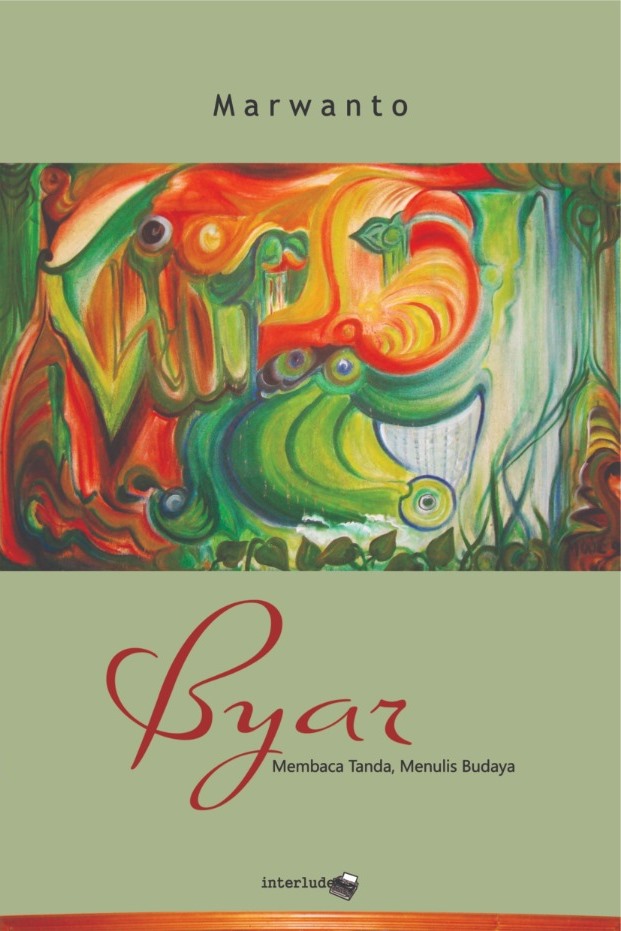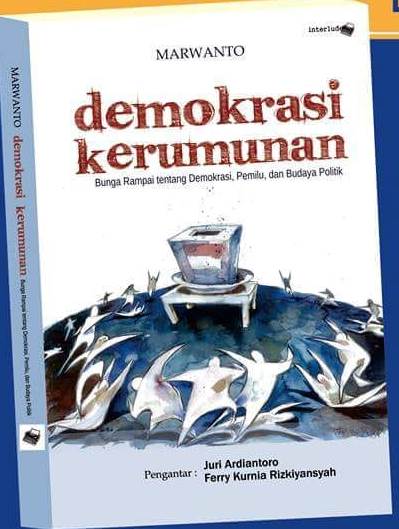Perempuan yang Diam Di Jembatan
( dimuat Koran MERAPI, 4 Juli 2010)
Cerpen Marwanto
Perempuan itu berangkat di pagi hari. Ketika sorot matahari masih menerobos pucuk-pucuk dedaunan. Dan ayam tetangga baru saja keluar dari kandang. Sambil menggandeng tangan Tole, anaknya yang tadi menghabiskan dua potong ketela, ia menggendong kayu bakar untuk dibawa ke pasar dekat terminal.
Menempuh jarak tiga kilometer tentu bukan perjalanan yang singkat. Apalagi sesekali Tole minta berhenti saat kakinya kelu dan wajahnya pucat. Sebenarnya sudah berulangkali emaknya melarang Tole ikut ke pasar. Tapi, di rumah hanya ada nenek yang jalannya sudah gemetar. Dua kakaknya telah bersiap ke sekolah. Tole tak mau kesepian, tak ingin pula resah. Ia ingin di pasar: yang banyak orang, jajanan, mainan, dan segalanya yang serba meriah.
“Tapi awas lho, jangan minta macam-macam ! Uang emak cuma cukup buat beli sayur dan tempe.” Pesan rutin emaknya sebelum berangkat.
“Iya, Tole cuma mau lihat orang jual mainan. kok”
“Boleh lihat, tapi jangan lama-lama”
Matahari sedikit di atas pucuk-pucuk daun kelapa. Hampir dua kilometer mereka meniti jalanan beraspal tanpa sandal. Keringat mulai mengucur dari wajah perempuan setengah baya itu. Belum, perempuan itu belum genap empat puluh tahun. Tapi semenjak ditinggal mati suaminya, ia jauh tampak lebih tua dari umur sebenarnya. Sesekali ia usap keringat yang meleleh di pipi tanpa bedak itu dengan sisa selendang yang digunakan untuk menggendong kayu bakar.
“Mak, nanti kita istirahat sebentar di jembatan ya ?”
Perempuan itu menjawab singkat” “he-em”. Lalu dari sorot matanya terlihat jelas lukisan peristiwa di masa silam. Setahun yang lalu, terjadi di lokasi pembuatan jembatan baru itu. Tak lama setelah anaknya yang pertama masuk SMP dan mertuanya keluar dari rumah sakit. Tapi takdir memang urusan Tuhan. Dan sejak itu ......
“Mak, kita sampai. Hore....hore....”
Suara Tole membuyarkan lamunan. Bocah itu berlarian kecil mendapati pemandangan yang diimpikan sepanjang perjalanan. Bola matanya tak hendak lepas dari mesin pengangkut alat berat yang tiap harinya mengerjakan pembangunan jembatan. Jembatan baru yang dibangun bersebelahan dengan jembatan lama karena bagian tengahnya ambrol lebih dari empat tahun lampau. Meski jembatan itu tergolong vital (penghubung satu-satunya jalur selatan Yogyakarta – Purworejo, Jawa Tengah), pemerintah propinsi sepertinya lamban menangani masalah ini. Dan selama empat tahun terakhir di atas bagian yang ambrol itu hanya dipasang papan dari kayu, sehingga cuma kuat dilewati mobil dan motor. Bus dan truk sudah lama absen dari tempat itu.
Dua tahun lalu jembatan baru itu mulai dibangun. Mengambil lokasi sekitar satu kilometer sebelah selatan jembatan lama yang telah rusak menahun. Tapi pengerjaan nya terkesan lamban. Tak ada yang tahu persis penyebabnya. Yang ada cuma praduga. Mungkin karena pembebasan tanah di sekitar bibir sungai yang berjalan alot. Mungkin karena pembangunan jembatan terpanjang di Jawa itu merupakan mega proyek sehingga deal-deal di tingkat atas begitu rumit. Ah, entahlah. Namun di kalangan masyarakat awam terlanjur beredar kabar bahwa lokasi pembuatan itu tidak tepat. Sebab menerjang “rumah buaya putih” yang terletak di tengah sungai
Mitos adanya makhluk halus bernama buaya putih itu memang diyakini betul oleh masyarakat sekitar. Semula pimpinan proyek memandangnya cuma semacam kelakar. Tapi, ia mulai berpikir lain, ketika di lokasi tersebut sering terjadi peristiwa aneh. Misalnya, tiba-tiba truk pengangkut beton macet tanpa sebab yang jelas. Dan, yang membuat miris banyak orang, di lokasi itu telah menelan korban lima orang kuli meninggal. Ah, mungkin kurang tepat jika disebut meinggal, tapi hilang. Ya, jasadnya mukswa (hilang) entah kemana.
Ketika dikonsultasikan ke “orang tua”-- orang yang dipandang punya “ilmu linuwih” -- disarankan supaya lokasi pembangunan jembatan itu dipindah. Maksudnya, lebih merapat ke jembatan lama, agar tak berpapasan dengan “rumah buaya pituh” yang membikin resah.
“Apa Simbah tidak bisa menjinakkan buaya putih itu ?”, tanya pimpinan proyek saat menghadap “orang tua” tadi.
“Wah, berat Tuan. Setahu saya, semua “orang tua” yang ada di Jawa ini tak ada yang mampu. Tapi, sebentar.....”
Orang tua itu berpikir keras. Keningnya yang sudah berkerut tambah sengkarut. Ia hendak mengemukakan sesuatu, tapi ada ragu.
“Tapi apa Mbah.....?”
“Emm, semoga saya tidak kuwalat. Kalau Tuan berani... Tapi kalau Tuan berani....”
“Kalau berani apa Mbah?”
“Kalau Tuan berani coba saja sowan Ngerso Dalem...”
“Lho, apa hubungannya ?”
Lalu orang tua itu menerangkan bahwa “buaya putih” itu hanya bisa dijinakkan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dan, semua orang Yogya maklum, bahwa Ngerso Dalem punya hubungan khusus dengan penguasa pantai selatan itu. Tapi entah mengapa pimpinan proyek tak juga datang konsultasi pada Ngerso Dalem. Akibatnya, ketika dengar pendapat dengan anggota Dewan tentang pengalihan lokasi pembangunan jembatan itu, ia dibantai kiri-kanan. Terang saja banyak anggota Dewan yang gerang sebab sudah berapa ratus juta anggaran dihabiskan secara mubadzir. Sampai akhirnya lokasi pembangunan jembatan itu pindah, tak ada yang tahu persis penyebabnya.
Sejak lokasi dipindah, pembangunan jembatan itu tampak lebih cepat dan mudah. Terlebih, orang-orang di sekitar banyak yang berdatangan. Tiap pagi dan sore di sepanjang jembatan lama itu tak pernah sepi dari orang yang bertandang. Walhasil, lokasi itu telah menjadi tontonan gratis masyarakat sekitar. Hilir mudik mesin-mesin berat dan para kuli, beton-beton raksasa membujur, ditengah hamparan sungai terlebar di Jawa dan pemandangan lepas ke selatan samudera putih nan luas, adalah satu rangkaian harmoni yang menghibur setiap pengunjung.
Perempuan itu, emaknya Tole, tak luput menjadi salah satu dari sekian puluh orang yang ikut berjejal. Apalagi ketika suaminya belum lama dinyatakan meninggal. Perempuan itu hampir tak pernah absen. Berdiri di tepi jembatan dengan tatapan mata mengarah ke tengah sungai. Sambil hatinya risau menerka: dimanakah gerangan suaminya itu mukswa. Bahkan sampai hari ke seratus sejak suaminya mukswa, hati perempuan itu masih tertambat di jembatan: setia menunggu.
Tapi kehadiran Teguh mengacaukan semuanya. Ya, ia adalah lelaki yang gagal mendapatkan cintanya. Sejak urung kawin dengan perempuan itu, hingga kini Teguh tetap membujang. Dan ketika Teguh mulai bergabung sebagai kuli seminggu yang lalu, perempuan itu menjadi jengah untuk melamun di tepi jembatan. Ia merasa tak nyaman melamunkan suaminya sementara ditengah-tengah kuli yang sedang bekerja ada Teguh -- berdiri dengan sorot tajam dan senyum hendak merengkuh.
Akhirnya perempuan itu memutuskan untuk tak lagi melamun di tepi jembatan. Ia hanya akan datang ke lokasi itu saat pagi masih suci. Belum dijarah oleh kuli-kuli. Baru ada kabut, dan sedikit orang lalu lalang hendak ke pasar atau kantor dengan laju kendaraan agak tergesa dan ngebut. Bukan kuli, apalagi Teguh yang kini ia waspadai. Seperti di pagi itu, ketika untuk kesekian kali ia melihat Tole riang berlarian kecil dan menari-nari.
Tubuh mungil bocah itu, bagai tupai yang melompat di dahan kelapa, dengan lincahnya menyelinap menyusuri keramaian pejalan kaki dan kendaraan yang lewat. Perempuan itu seakan lepas dari beban melihat buah hatinya riang-gembira. Ia turunkan kayu bakar dari gendongan. Lalu, matanya tak berkedip menatap ke tengah sungai. Ya, tempat yang diperkirakan sebagai rumah buaya putih dimana suaminya mukswa. Ia hanyut dalam kenangan.
Namun lamunan itu pecah oleh derit ban yang direm mendadak. Perempuan itu segera menoleh ke arah suara. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika melihat Tole tersungkur dengan kepala bersimbah darah. Lalu berguling-guling dan akhirnya mencebur ke sungai. Tanpa melihat kiri-kanan perempuan itu mengambil langkah seribu. Dan ketika sampai di tempat anaknya tersenggol mobil, dilihatnya Tole telah lenyap digulung ombak sungai.
Orang-orang berkerumun histeris, lalu memberi komentar sesukanya.
“Anak itu telah menyatu dengan bapakya di rumah buaya putih.....”
“Ya, daripada melihat emaknya ada apa-apa dengan Teguh .....”
“Tapi, mengapa masih ada korban jatuh ?”
Beberapa bulan kemudian, ketika acara peresmian jembatan dilangsungkan, diantara ratusan pengunjung yang berjejal, perempuan itu – emaknya Tole – seakan ingin maju mendekat pejabat yang menggunting pita. Lalu dengan iba bercampur amarah ia akan bertanya: “Mengapa selalu ada korban yang jatuh ?”***
Rabu, 07 Juli 2010
Langganan:
Postingan (Atom)